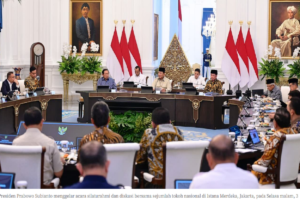Asvi yang mengawali kariernya sebagai wartawan, redaktur pelaksana sebuah majalah olahraga, menyebut nalar kritis tidak akan pernah tumbuh di ruang yang
dikendalikan.
Meninggalkan profesi watawan, bergabung di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), lalu melanjutkan studi doktoralnya di Prancis, ia menekuni sejarah
Asia Tenggara kolonial di bawah bimbingan sejarawan erkemuka, Deni Lombard.
Di situlah nalar sejarahnya ditempa. Ia kembali ke tanah air dengan semangat meluruskan sejarah yang bengkok oleh politik.
“Saya mendukung penulisan ulang sejarah Indonesia, tapi istilah sejarah resmi itu keliru. Sejarah bukan milik negara, apalagi pemerintah,” tegasnya.
Prof. Asvi menyoroti absennya guru sejarah dalam tim penyusun. Padahal merekalah yang akan menggunakan buku tersebut di kelas, menyampaikannya kepada siswa.
Ia menyebut sejarah bukan hanya soal akurasi, tapi juga soal pedagogi, cara kita mewariskan kesadaran sejarah pada generasi muda.
Kebohongan Kolektif
Prof. Asvi kerap dituding terlalu keras menentang versi sejarah negara. Namun bagi dia, diam justru bentuk pengkhianatan terhadap masa depan.
“Kalau sejarah terus ditulis untuk menyenangkan penguasa, maka bangsa ini akan terus hidup dalam kebohongan kolektif,” katanya.
Ia tidak memusuhi negara, tetapi ia menolak tunduk pada distorsi narasi. Baginya, sejarah adalah ruang publik yang harus dibuka, bukan ditutup. Ia menyerukan agar masyarakat tidak hanya membaca sejarah, tapi juga mempertanyakan ditulis untuk kepentingan siapa.
Kini, di usia senjanya, Prof. Asvi telah memasuki masa purnabakti sebagai peneliti. Namun ia tidak pensiun dari urusan sejarah. Ia tetap hadir di seminar, diskusi publik, dan ruang-ruang editorial untuk mengawal integritas sejarah bangsa.
“Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Tapi saya tidak bisa diam melihat sejarah terus dipakai sebagai alat legitimasi kekuasaan,” ucapnya.
Di tengah kegiatan penulisan ulang sejarah nasional, ia memilih berdiri di luar arus. Ia tidak menolak penulisan ulang sejarah Indonesia, asal ditulis dengan jujur.
Ada beberapa hal yang harus diluruskan menurut Asvi. Misalnya peran presiden Habibie, Gus Dur, dan Megawati. Karena memerintah hanya sebenatar, seakan akan hanya penuh dengan masalah
“Sementara kegiatan pembangunan dimonopoli oleh SBY dan Jokowi,” katanya.
Sejarah Standar
Prof. Asvi juga menyatakan bahwa penulisan sejarah nasional semestinya bersifat standar (standard history), bukan resmi (official history).
Perbedaan ini bukan soal istilah teknis, tapi menyangkut fondasi epistemologis sejarah itu sendiri. Ia juga menyoroti bahwa proses teknis penulisan yang kini berjalan belum mencerminkan semangat partisipatif.
“Drafnya sudah keluar Januari, tapi masukan baru mau ditampung Mei. Ini bukan revisi biasa. Ini harus dibangun dari awal dengan fondasi yang benar.”
Kegelisahan Prof. Asvi paling tampak ketika membahas substansi sejarah yang dilompati, dihapus, atau dipilah-pilah. Ia menyebut beberapa peristiwa penting yang hilang atau diabaikan.
Misalnya Kongres Perempuan yang nyaris tidak disebut berdampingan dengan Sumpah Pemuda. Pemberontakan PRRI/Permesta yang absen tanpa alasan. Lepasnya Timor Timur. Juga Reformasi 1998 yang semestinya ditulis sebagai gerakan kolektif, bukan kronologi elit.
“Sejarah kita bukan hanya soal kemenangan, tapi juga soal luka. Kalau kita menutup-nutupi pemberontakan, pelanggaran HAM, dan kegagalan, artinya kita menyusun narasi yang manipulatif,” ungkapnya.
Kesalahan Lama
Dalam konsep kerangka yang diterbitkan Kementerian Kebudayaan Januari 2025 lalu, Prof. Asvi melihat terlalu banyak sisi sejarah yang dirampingkan atau bahkan dihilangkan.
Ia mencontohkan pengakuan negara atas 12 pelanggaran HAM berat yang disampaikan Presiden Jokowi di Istana pada 2023.
“Mengapa tidak tercermin dalam konsep buku ini. Bukankah pelajaran sejarah harus memberi ruang bagi pemulihan, bukan pelupaan ?” katanya.
Ia mengangkat kisah tragis ribuan orang yang dibuang ke Pulau Buru tanpa proses pengadilan, kerja paksa, tanpa status hukum, tanpa rehabilitasi.
“Mereka perlu dimasukkan dalam sejarah kita. Karena sejarah tak hanya mencatat kejayaan, tapi juga luka yang tak boleh diulang,” tambahnya.
Sejarah nasional menurut Asvi juga pernah disusun dalam enam jilid. Tapi sejarah penulisan sejarah itu sendiri menyimpan pelajaran pahit. Sartono Kartodirdjo, yang awalnya jadi penyunting, mundur karena masukan akademiknya tidak diterima.
Ia khawatir pola serupa kini terulang. Tim penulis dibentuk, kritik ditampung secara seremonial dalam FGD, tapi substansi tak bergeser.“Masukan bukan ditempel belakangan. Dari awal konsep harus=menyeluruh,” katanya.
Berdasar Tema
Prof. Asvi menyarankan agar tema-tema besar yang menyentuh semua rezim dan tokoh ditulis sebagai benang merah sejarah nasional, bukan sekadar timeline kepemimpinan. Untuk menghindari jebakan glorifikasi individu, dengan pendekatan tematik, bukan kronologis.
Ia menyarankan agar penulisan sejarah Reformasi berfokus pada empat tema utama. Pertama : Reformasi dan perubahan UUD 1945.
Kedua, krisis ekonomi 1997–1998 dan penanganannya. Ketiga pemisahan Timor Timur. Keempat pandemi COVID-19.
“Menulis berdasarkan tokoh itu problematik karena kita akan tergoda membuat pahlawan dan pesakitan. Kalau berdasarkan tema, kita bisa bahas substansi bangsa tanpa bias personal,” katanya.
Sejak masa Orde Baru, Indonesia memiliki kebiasaan menyederhanakan sejarah—memangkas yang berpotensi mengganggu dan memoles yang bisa memperkuat legitimasi.
Tapi di masa reformasi, ruang publik seharusnya membuka jalan lain: ruang perdebatan yang sehat, ruang kritik yang dianggap kontribusi, bukan ancaman. Prof. Asvi mengingatkan bahwa tugas negara bukan lagi mengontrol sejarah, tapi memfasilitasi keberagamannya.
Ia mengakui bahwa sejarah—khususnya sejarah nasional—memang selalu melahirkan perdebatan. Tapi itu bukan kegagalan, justru tanda bahwa bangsa ini hidup dan berpikir.
Mencatat Bukan Menghakimi
Prof Asvi Warman Adam mengingatkan perlunya mencatat pelanggaran HAM berat secara eksplisit dalam buku sejarah nasional.
Meski tidak semua pelaku bisa lagi diadili karena waktu dan situasi hukum, sejarah tetap berkewajiban merekam dan menyampaikan.
“Pernah ada proses hukum, seperti dalam kasus Timor Timur, tapi mayoritas pelaku dibebaskan. Meskipun demikian, pencatatan sejarah tetap harus dilakukan agar kesalahan tidak berulang,” tegasnya.
Ia menggarisbawahi bahwa mencatat bukan berarti menghakimi. Sejarah bukan ruang balas dendam, tapi ruang kesadaran kolektif agar bangsa tidak kembali pada kegelapan yang sama.
Prof. Asvi mengangkat contoh menarik, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa Peristiwa Madiun 1948 bukan murni ulah PKI, tapi provokasi Belanda.
Sebuah narasi yang secara diametral bertentangan dengan versi resmi Orde Baru. “Ini momen penting. Kalau presiden sendiri sudah membuka ruang reinterpretasi, kenapa sejarah kita masih kaku dan hitam putih?” tanyanya.
Demikian juga dengan wacana pengangkatan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Ketika Presiden membuka peluang, mestinya bukan sekadar retorika. Peluang itu seharusnya ditindaklanjuti, bukan dibiarkan jadi basa-basi politik.
Tak Bisa Semua Senang
Bagi Prof. Asvi, harapan utama ke depan adalah keterbukaan dalam proses penulisan sejarah. Tapi ia tak menutup mata, waktu terbatas, draf nyaris final, dan ada kemungkinan kritik tidak semua bisa ditampung.
Namun satu hal penting yang ia garis bawahi, jangan jadikan waktu atau tekanan politik sebagai alasan membungkam isi.
“Jangan sekadar mengejar target cetak. Ini catatan sejarah bangsa. Kalau ada bagian penting yang belum dimasukkan, lebih baik ditunda atau ditambahkan secara bertanggung jawab,” katanya.
Sejarah nasional Indonesia akan terus ditulis dan ditafsirkan ulang, dan itu adalah keniscayaan dalam negara demokrasi. Tapi saat sebuah proyek sejarah besar dilakukan negara, seperti sekarang, publik harus waspada, apakah ini pencerdasan, atau narasi kekuasaan.
“Saya percaya, sejarah bukan untuk menyenangkan semua orang. Tapi sejarah yang baik adalah yang membuat kita semua belajar.” Jelasnya.