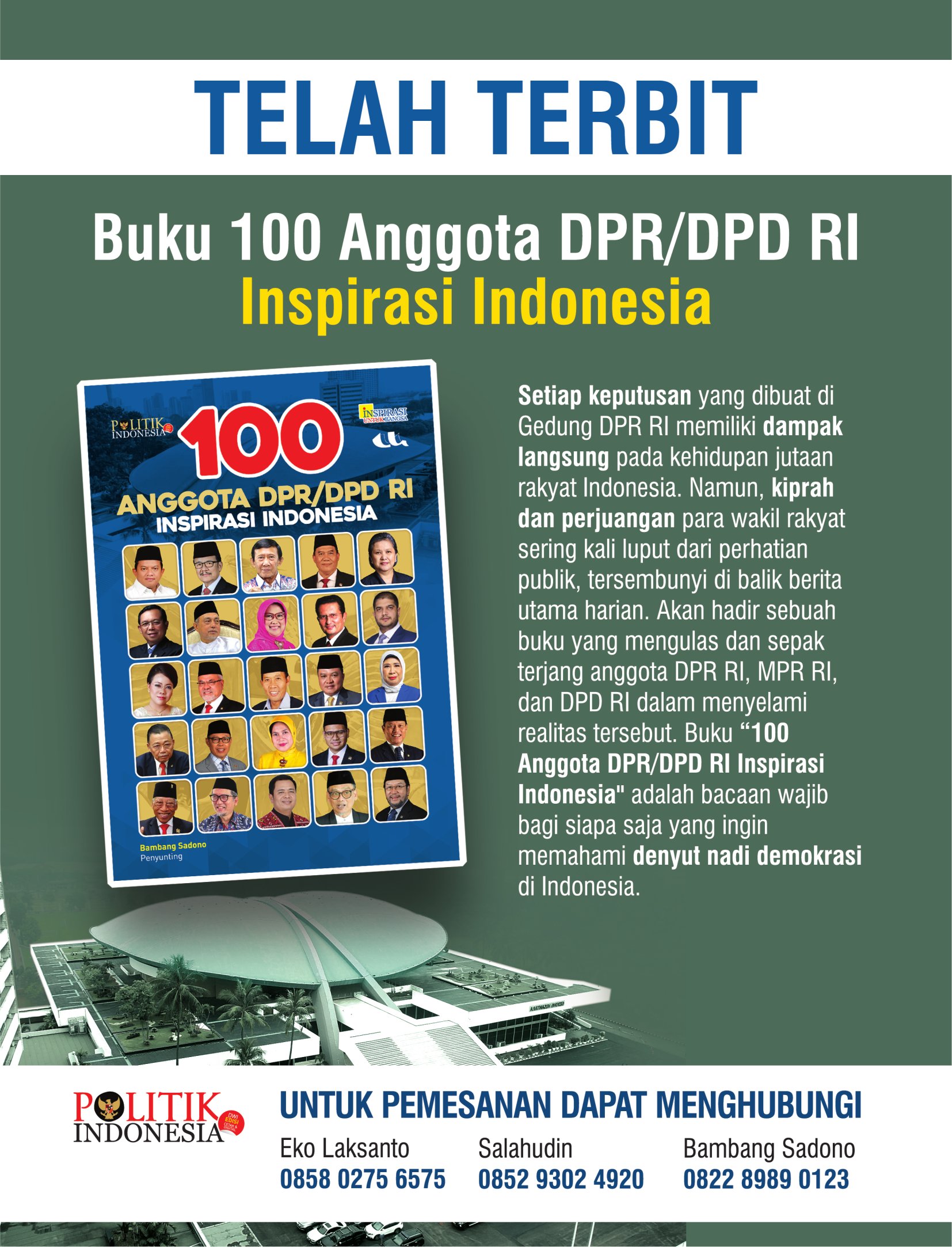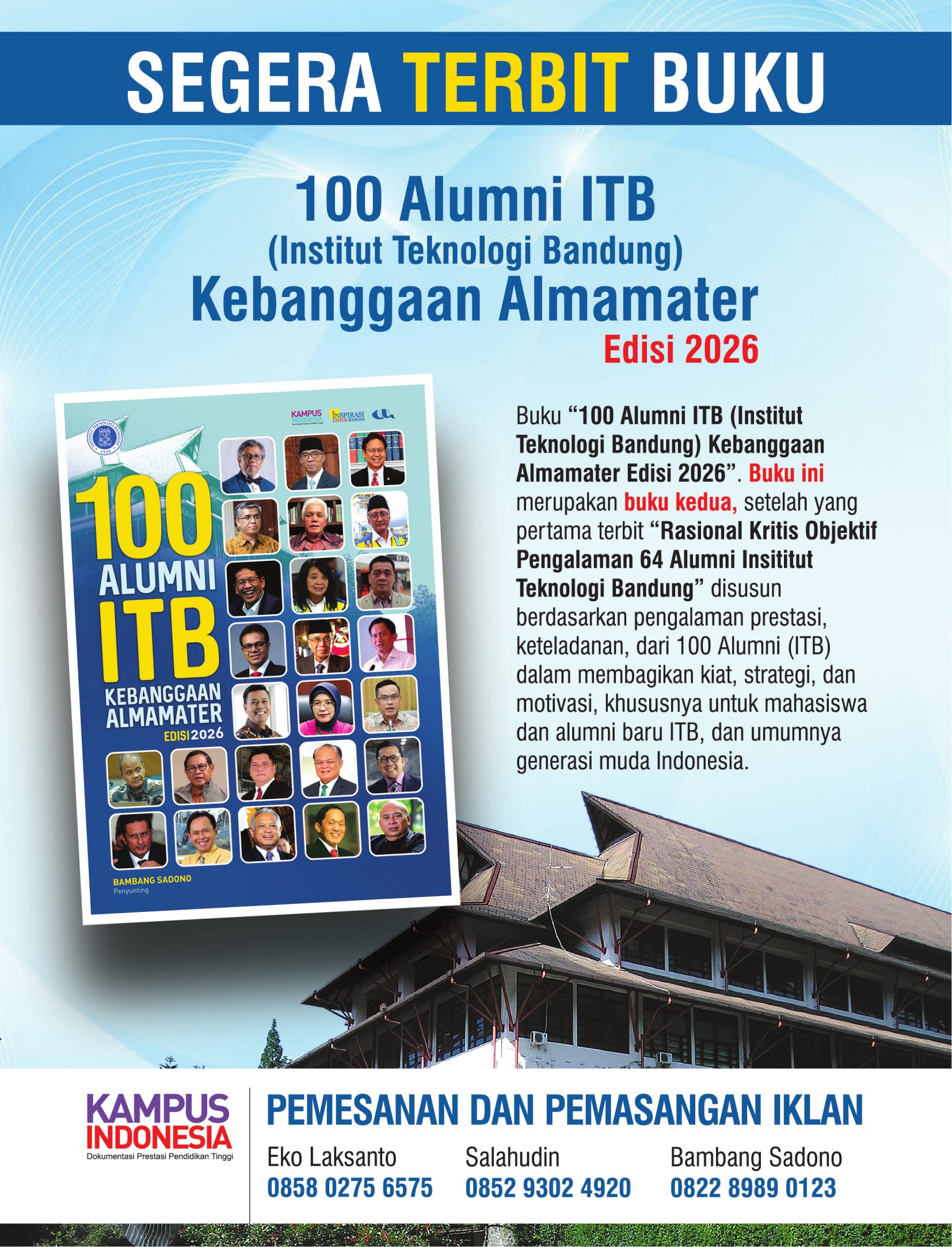Dunia gempar, karena Trump mengabaikan World Trade Organization (WTO) yang telah membuat ketentuanketentuan yang membatasi setiap negara, sehingga mereka tidak bisa sembarangan menaikkan tarif.
Trump punya alasan mendesak untuk mengabaikan aturan. Bisa jadi ia cemas lantaran pengangguran di negaranya makin tinggi. Lapangan pekerjaan yang seharusnya milik warga AS, hilang lantaran banyak perusahaan merelokasi pabrik-pabriknya ke negara lain.
Alasannya perusahaan tersebut, kalau tetap berproduksi di negaranya, margin keuntungannya kecil. Sebabnya banyak, upah yang pasti mahal, asuransi, dan lainnya yang tentu saja berbiaya tinggi.
Sehingga perusahaan-perusahaan tersebut banyak yang berlabuh ke negara lain, seperti China, Vietnam, India, Indonesia, dan banyak negara lain.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) itu mencontohkan, ada sepatu merek terkenal yang punya pabrik di Indonesia. Kalau dibuat di Amerika Serikat, biaya produksinya sangat tinggi, karena gaji tenaga kerja yang harus dibayarkan tinggi. Sehingga mereka melempar ke Indonesia, ke Vietnam, dan negara lainnya.
“Memang kalau misalnya kita lihat ekspor kita ke Amerika jadi besar. Tapi itu bukan sepatu buatan Cibaduyut, bukan, itu perusahaan Amerika sendiri, Itu biasa di era globalisasi,” katanya.
Beratkan Rakyat Amerika
Trump mengatakan “If we want to make America great again maka kita harus kembalikan kemakmuran itu.” Caranya bagaimana? Dulu di masa jabatan pertamanya, Trump sudah mengenakan tarif tinggi ke China.
Harapannya adalah perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang melakukan ekspor itu balik kandang. Tetapi itu tak terjadi. Mereka pergi ke negara lain
yang tidak kena tarif yaitu Vietnam.
Indonesia pun sebenarnya sudah bersiap-siap, dengan melahirkan UU Ciptakerja untuk memudahkan investor. Prof Hikmahanto, tak habis pikir dengan kebijakan Trump tersebut.
Logikannya sederhana saja, apakah dengan pengenaan ke Indonesia misalnya, 32 %, yang bakal membayar tarif 32% rakyat Indonesia? Tidak. Justru rakyat
Amerika yang bakal membayar.
Bisa dibayangkan kalau di Amerika Serikat permintaan komoditas itu masih tetap ada, misalnya sawit, padahal tidak bisa mencari dari negara lain, berarti yang
harus membayar lebih mahal, rakyat Amerika Serikat.
Banyak perempuan juga protes karena tidak bersedia untuk membayar lebih besar baju-baju yang mereka kenakan. Karena sebagian besar baju-baju mereka buatan China.
Akhirnya kebijakan tersebut seperti bumerang, berbalik pada diri mereka sendiri. Itu yang membuatnya tak paham dengan langkah Trump tersebut. Andai kebijakan tarif tersebut dilakukan bilateral, Indonesia-AS, misalnya, masih memungkinkan.
Bahkan bisa digunakan untuk mendikte suatu negara untuk menurunkan tarif masuk produkproduk Amerika. Mereka bisa mendikte untuk meningkatkan
pangsa pasar, dengan tidak mengganggu konsumen domestik.
Tetapi kalau diterapkan, bersamaan, sepertinya mustahil. Menurutnya kebijakan tersebut akan dilawan banyak negara. China membalas, diikuti oleh Uni Eropa, Kanada, dan banyak negara lain. Sedangkan Indonesia mengirim tim negosiasi.
Menurut dia, tim negosiasi baru efektif kalau bicara soal bilateral, tapi persoalan tarif sudah bersifat multilateral pada saat bersamaan. Jadi tim negosiasi sebenarnya tidak ada artinya.
Tidak Perlu Mengemis
Jadi sebenarnya Indonesia tidak perlu negosiasi. Ia menyarankan negara perlu menjalin koalisikoalisi dengan negara yang punya produk sama. Misalnya Presiden Prabowo pergi ke Malaysia, bertemu Anwar Ibrahim, mengajak koalisi untuk bersama-sama menurunkan tarif.
Menurutnya langkah Vietnam termasuk “nakal”. Vietnam langsung buruburu bilang, “Saya nolkan semua ke Amerika.” Dengan begitu, kapasitas produk sepatu sneakers dari Vietnam akan dibesarkan, sedangkan di Indonesia, akan diciutkan.
Karena pada akhirnya, rakyat Amerika Serikat yang akan membayar lebih mahal. “Nah saya enggak tahu, Trump masih percaya diri dengan tim ekonominya, mungkin pengenaan tarif itu akan memperbaiki situasi Amerika,” katanya.
Langkah Trump tersebut memang bisa dibaca sebagai strategi memperbaiki Amerika dalam konteks untuk mengendalikan perdagangan internasional. Bisa jadi ia berpikir dengan kebijakan tersebut banyak negara berbondong-bondong untuk ‘mengemis’.
Mereka boleh merasa masih mendominasi dunia dengan pangsa pasar kelas menengah yang kuat. Indonesia pun merasa terimbas oleh kebijakan tersebut.
Namun untuk menentukan langkah, sebaiknya menunggu negara lain.
Toh imbas buruk kebijakan tersebut dialami oleh banyak negara. Rakyat Amerika juga protes, turun ke jalan di Washington DC, New York. Artinya, mereka juga
tidak setuju dengan kebijakan Trump.
Mereka tidak setuju Trump menaikan tarif, mereka juga tidak sepakat pemerintahnya mendeportasi pendatang ilegal, atau mendeportasi orang yang berpihak pada Palestina. Belum lagi dengan keberadaan Elon Musk yang membuat banyak orang Partai Republik, balik badan.
Dengan indikator tersebut, Prof Hikmahanto meminta pemerintah menunggu selama 3 bulan. Dalam masa itu, melihat reaksi dari negara-negara lain. Indonesia tinggal ikut arus besar dunia, berkoalisi, dan bertemu dengan negara-negara yang mempunyai komoditas sama yang .
Prinsipnya, tandas dia, Indonesia bisa memahami situasi, saling berbagi informasi dengan negara lain, dan kalau perlu menginisiasi untuk melakukan evaluasi terhadap langkah yang ditempuh menghadapi kebijakan Trump.
“Jadi jangan kemudian kita juga ikut-ikutan panik. Karena, pertama, Trump harus menghadapi masyarakatnya. Kedua Trump juga harus menghadapi serangan dari banyak negara-negara sekutunya. Sekarang Uni Eropa, mungkin posisinya sama China,” papar dia.
Dan yang ketiga, dihajar bursa saham. Padahal masyarakat Amerika banyak mengandalkan bursa saham sebagai uang pensiun, atau sebagai sebagai usaha untuk mendapatkan keuntungan dengan bermain saham. Bahkan ada yang sampai rugi triliunan rupiah garagara bursa saham yang rontok. Jadi bursa saham ini tidak bisa dikecilkan.
Kematian Hukum Internasional
Secara tegas ia menandaskan bahwa langkah Trump jelas melanggar ketentuan World Trade Organization (WTO). Dalam organisasi perdagangan dunia
tersebut ada ketentuan bahwa suatu negara tidak bisa sembarangan menaikkan tarif.
Malah diatur agar anggota organisasi bersepakat untuk menghilangkan tarif. Jadi perdagangan antar negara diharapkan menjadi perdagangan antar provinsi, tanpa tarif apa pun. Seperti Jawa Tengah menjual beras ke Lampung, tidak ada tarif dari Pemda Lampung.
Hal itu dituangkan dalam kesepakatan WTO. Kemudian kalau ada pelanggaran, diselesaikan di Dispute Settlement Body (DSB) yang di bentuk WTO. Indonesia
pernah bersengketa dengan Uni Eropa terkait nikel dan kelapa sawit.
Hanya saja, kalau sudah terkait negara-negara besar seperti Amerika Serikat, biasanya diabaikan. Hukum internasional diabaikan, yang berlaku hukum
rimba, siapa yang kuat dia yang menang.
“Saat Tump perang tarif dengan China, apakah kemudian China pergi ke WTO? Enggak. Apa Amerika pergi ke WTO? Juga enggak kan,” ujar dia.
Padahal, lanjut dia, negaranegara kecil selama ini selalu diceramahi oleh negara seperti Amerika Serikat, untuk tunduk pada hukum internasional. Tetapi giliran negara besar punya kepentingan, hukum dilupakan.
Jadi yang perlu dilakukan, mencoba memahami sikap negara-negara lain terhadap kebijakan Trump. Sekalipun demikian, Indonesia harus melapor ke WTO seperti negara-negara lain. Walaupun ujung dari upaya tersebut, sudah tahu, tidak ada artinya.
Tetapi setidaknya, Indonesia harus menempuh mekanisme hukum yang ada. Imbas pengabaikan hukum internasional oleh negara-negara besar, menurut Prof Hikmahanto menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap hukum internasional.
Bahkan bisa jadi hukum internasional dianggap tidak ada. Hukum Internasional mati, karena selama ini sekadar untuk menjustifikasi, atau membenarkan tindakan suatu negara.
Tetapi sebagai aturan yang harus disepakati, aturan yang bagi pelanggarnya bakal dipersalahkan dan dijatuhi hukuman, tidak ada lagi. Karena yang berlaku sekarang adalah keputusan-keputusan sepihak dari negara-negara besar.
Itu berpotensi memunculkan kekacauan. Ia bahkan menyebut Amerika Serikat di bawah Presiden Trump bisa dianggap menjadi negara berkembang. Karena pemimpinnya diktator, dan pengambilan keputusannya tanpa dikaji lebih mendalam. Jadi tidak bisa Amerika Serikat disebut sebagai pemimpin dunia yang langkahnya bakal diikuti negaranegara lain.
Era Survival
Menurut Prof. Hikmahanto, saat ini yang penting, tiaptiap negara harus berpikir tentang survival, termasuk Indonesia. Jadi harus melihat kepentingan
nasional. Tidak ada cerita pro barat, atau pro timur. Era tersebut sudah selesai. Tidak ada lagi cerita tentang membangun kebersamaan.
Eranya adalah era survival. Dan kita bisa lihat, Amerika untuk bisa survive, dia bisa abaikan hukum, hukum internasional. Negara-negara seperti China, mereka bilang akan tunduk pada aturan, tapi kalau kepentingan mereka ada.
“Tapi seperti pada sembilan garis putus-putus, mereka akan bilang tidak akan tunduk pada hukum internasional. Nah ini contoh tidak baik bagi negara-negara yang tidak memiliki kekuatan yang besar, seperti Amerika atau China,” paparnya.
Pada akhirnya ketidakpercayaan terhadap hukum internasional berpotensi memicu resesi dunia, konflik-konflik kawasan, dan menjadi bibit-bibit perang dunia. Demikian juga kebijakan Trump. Prof Hikmahanto memprediksi andai saja kebijakan Trump bertahan sampai 1 tahun, bakal memicu resesi.
Tapi kalau bertahan hanya 3 bulan, tidak akan memicu persoalan lebih buruk. Hanya saja persoalannya, andai Amerika Serikat yang dianggap sebagai kekuatan
penyeimbang tidak dipercaya lagi, siapa yang bakal menjadi penyeimbang bagi China?
Andai China mendominasi kawasan, dan menggunakan kekerasan senjata, dan lain sebagainya, bagaimana menghadapinya? Itu tantangan tersendiri, apalagi Trump menyatakan bahwa menjaga stabilitas kawasan hanya buang-buang duit.
Jadi ujungnya adalah bagaimana setiap negara membangun daya tahannya sendirisendiri, baik di bidang ekonomi maupun pertahanan.
Tidak Perlu Negosiasi
Prof Hikmahanto memperkirakan persoalan ini akan bermuara pada dua hal. Pertama, lihat tiga bulan ke depan, apakah kebijakan Trump tetap bisa dijalankan atau dia akan berubah?
Perubahan tersebut, ada kemungkinan bahwa kebijakan tarif tersebut hanya menyasar China, tidak negara-negara lain. Kalau itu yang terjadi, berarti back to bussiness usual.
Kedua, kalau tidak terjadi seperti itu, Indonesia harus bisa mengantisipasi. Tidak perlu negosiasi, karena pemerintahan Trump sudah menyatakan tidak ada pintu negosiasi. Jadi Indonesia mempersiapkan diri, seperti melakukan perubahan terhadap APBN, bagaimana shifting agar bisa punya pangsa pasar.
BUMN, perusahaan-perusahaan swasta diberdayakan untuk go internasional dan tidak sematamata bergantung pada pangsa pasar Amerika Serikat. Selain tarif, ada keberatan soal non tarif barrier yang menyebabkan seolah-olah ada tarif tambahan.
Sejatinya, Amerika Serikat sah-sah saja menuntut Indonesia untuk memperbaikinya. Namun menurut Prof Hikmahanto, sejatinya non tarif barier tersebut, bukan berdasarkan aturan di Indonesia.
Misalnya, Indonesia bisa buat aturan bahwa barang yang masuk dari Amerika Serikat ke Indonesia harus bersertifikasi SNI. Mereka marah dan mempertanyakan apakah standar SNI Indonesia lebih bagus daripada misalnya SNInya Amerika Serikat.
Kemudian semua obat-obatan dari Amerika Serikat harus bersertifikasi BPOM. Mereka mempertanyakan apakah FDA rendah dari BPOM? Hal itu mungkin dianggap sebagai non tarif barrier.
“Nah yang saya khawatirkan adalah berkaitan dengan masalah pungli, sehingga gara-gara masalah pungli, dianggap sebagai non tarif barrier,” katanya.
Barang dari luar negeri masuk ke Indonesia karena pungli jadi harganya lebih mahal, karena lebih mahal maka barang itu tidak kompetitif dengan misalnya produksi dalam negeri ataupun produksi dari negara lainnya.
Prof Hikmahanto melihat geger dunia ini semata gaya Trump, yang merasa bahwa pangsa pasar mereka besar dan diperebutkan banyak negara. Sehingga, Amerika Serikat bisa menggunakan instrumen tarif untuk mendikte negara-negara lain tanpa dianggap melakukan kolonialisasi atau penjajahan.
Ini sebetulnya juga intervensi terhadap kedaulatan suatu negara. Amerika Serikat sepertinya memberikan keistimewaan ke Indonesia. Tapi mereka mengajukan berbagai macam syarat yang harus dipenuhi.
Negeri adi daya itu tahu apabila neraca perdagangannya defisit, tapi mereka dengan berbagai instrumen bisa mendikte negara lain. Seperti menghadapi China. Trump menolak apabila Negeri Tirai Bambu itu dianggap sebagai negara berkembang.
“Enak aja negara berkembang dia ini sudah negara maju, dia bisa ngalahin kita,” katanya.
Termasuk Indonesia yang kegirangan ketika disebut negara maju. Keliru kalau cara berpikirnya seperti itu. Padahal itu merupakan dalih Amerika Serikat di bawah Trump akan mencabut tarif istimewa yang selama ini dijadikan instrumen untuk mengendalikan Indonesia.
Karena kalau instrumen tersebut dicabut, bukan berarti Indonesia kemudian menjadi negara maju. “Ini dialami semua negara. Karenanya, kalau saya sebagai
balasan, kita kenakan sekian persen, sekian persen, sekian persen, kan begitu pokoknya di atas 10% lah rata-rata,” katanya.
Ia kembali menegaskan bahwa dampak terbesar dari kebijakan Trump sebenarnya dirasakan warga Amerika Serikat. Eskalasi ketidakpuasan tersebut kemungkinan besar bakal dipresentasikan dalam bentuk aksi turun ke jalan. Bahkan saat ini sudah ada inisiasi untuk mengimpeachment Trump.
Rakyat Amerika Serikat tidak puas dengan sepak terjang Trump. “Nah yang saya khawatirkan, kalau itu bergulir terus sampai pada satu titik, tinggal Trump mau bertahan
tapi menghadapi gelombang demonstrasi, gelombang permasalahan dari kongresnya atau dia mengubah. Atau pada titik tertentu, Trump harus turun karena
diimpeach!” katanya.