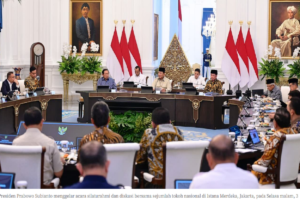Dalam kaitan ini, terlebih dahulu terpaksa harus menghapus kata ‘obyektif’; karena sudut, cara, jarak dan resolusi pandang tidaklah mungkin netral, tapi selalu dibangun berdasar pilihan sikap yang wataknya subyektif. Suka atau tidak suka, mendukung atau menentang. Data dan fakta obyektif pada dasarnya hanya dipakai dan ditafsirkan untuk melayani subyektifitas landasan awal tersebut.
Oleh karena itu masalah utamanya adalah masalah penafsiran. Penafsiran yang akan menyelusup masuk untuk memilah dan memilih data dan fakta, sekaligus mengangkat dan memberi makna padanya. Bahkan sangat mungkin, data dan fakta ‘obyektif’ yang sama, dibaca dengan tafsir yang bertentangan secara diametral oleh dua subyek dengan dua kepentingan yang berbeda.
Meski demikian, perkembangan ilmu sejarah modern justru memberi ruang yang cukup terhormat bagi muatan subyektif semacam ini. Perkembangan lebih lanjut dari apa yang diwacanakan oleh Edward W Said, bahkan menyorongkan orang pada keharusan untuk menengok sisi tafsir subyektif sebagai salah satu rujukan utama dalam membaca realitas sejarah. Penulisan sejarah baru dianggap berharga bila sisi tafsir ‘subyektif’ (subyektif sekaligus dalam pengertian literalnya) diberi tempat terhormat.
Wacana yang lantas dielaborasi oleh salah satu bidang kajian sejarah yang dikenal sebagai ‘sub- altern studies’, malah mulai menempatkan ruang tafsir subyektif sebagai salah satu tolok ukur utama untuk menilai kesahihan penulisan sejarah.
Tafsir arus utama, yang acap identik dengan idiom ‘sejarah di tulis oleh (subyektivitas) pemenang’, akan diuji dan dikritisi lewat tafsir pinggiran yang muncul dari subyektivitas mereka yang tersingkir. Pada tahap ini, kritisisme sejarah kemudian berkembang menjadi kritisisme terhadap muatan subyektif masing-masing penafsir terhadap data dan fakta ‘obyektif’ yang mereka pilah dan pilih.
***
Kembali ke masalah Soeharto. Sebagai sosok yang pernah berkuasa selama 32 tahun, justru mengherankan bila Soeharto hanya melahirkan kelompok yang suka dan mendukung saja, tanpa mereka yang tidak suka dan menentangnya. Semua pemimpin di mana pun dan dalam kondisi bagaimana pun pasti melahirkan pasangan kelompok semacam ini. Itu lumrah. Jadi kontroversi yang mengiringi usulan dan penetapan Soeharto sebagai pahlawan pun tak amat-amat mengejutkan.
Untuk sementara mari kita lolosi muatan subyektif para penafsir, agar memperoleh gambaran tentang data dan fakta ‘obyektif’nya. Fakta ‘obyektif’ yang diamini baik oleh yang suka dan mendukung, mau pun oleh yang tidak suka dan menentang.
Ambil beberapa contoh yang menonjol. Mulai tahun 1974 misalnya, secara massif rezim Soeharto berhasil membangun sekolah dasar yang kemudian dikenal sebagai SD Inpres di hampir seluruh pelosok Indonesia. Harus diakui kebijakan ini menandai fase baru pendidikan bagi rakyat Indonesia, yang sebelumnya sempat terseok karena keterbatasan sarana fisik.
Di sisi lain, sejak 1975 diluncurkan program bea siswa Supersemar, yang memberi kesempatan anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Harus diakui, program ini berhasil melahirkan banyak profesional yang kemudian terjun ke berbagai bidang sampai sekarang.
Di bidang kesehatan, sejak tahun 1970an rezim Soeharto menerapkan kebijakan untuk membangun Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di tiap kecamatan. Pada tahun 1984, layanan ini diperluas dengan mendirikan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), yang dimaksud untuk mempermudah penduduk pedesaan mendapatkan layanan kesehatan. Kedua lembaga ini juga merupakan fase baru dalam bidang layanan kesehatan. Dengan biaya murah, kedua lembaga ini memberi kesempatan rakyat untuk lebih mudah menjangkau layanan kesehatan bila dibutuhkan.
Di sisi lain, rezim Soeharto juga membangun banyak bendungan untuk menghidupkan sektor pertanian. Dan di saat bersamaan digalakkan apa yang biasa disebut sebagai ‘revolusi hijau’, lewat program Bimas (Bimbingan Masyarakat) dan Panca Usaha Tani. Lewat program ini, para petani didorong untuk mengadopsi teknologi pertanian modern, melalui penggunaan bibit unggul, pupuk kimia, pestisida, dan mengoptimalkan sistem irigasi agar mampu meningkatkan produksi pangan.
Sementara pembangunan infrastruktur transportasi darat dan laut, oleh rezim Soeharto difokuskan untuk mendukung swasembada pangan dan pembangunan ekonomi. Banyak jalan dan jembatan dibangun untuk mendukung konektivitas dan distribusi barang. Dan, mengingat peran penting transportasi laut dalam menghubungkan wilayah- wilayah di Indonesia, berbagai pelabuhan dibangun atau direhabilitasi oleh rezim ini.
Di luar itu semua, banyak hal yang juga telah dilakukan terkait sektor keagamaan. Mulai dari diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) pada tahun 1969 dan direvisi pada tahun 1975, yang mengatur pendirian rumah ibadah. Peraturan ini, merupakan bagian dari kerangka regulasi infrastruktur keagamaan yang mengedepankan ketertiban umum dan stabilitas, tentu saja dengan pendekatan keamanan yang kuat.
Untuk perbaikan dan pengelolaan infrastruktur serta layanan yang mendukung pelaksanaan ibadah haji, termasuk asrama haji dan fasilitas terkait; manajemen urusan haji diletakkan di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (sebelumnya Direktorat Jenderal Haji) di Kementerian Agama.
Rezim Soeharto juga membentuk MUI sebagai wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan Muslim pada tahun 1975. Pembentukan lembaga ini dimaksud untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan umat Islam.
Kecuali itu, juga mencoba melakukan transformasi dan memberi pengakuan yang lebih besar terhadap lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah dalam sistem pendidikan nasional dengan mengintegrasikan pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan formal.
Dan yang tak kalah penting, sejak 1982 Soeharto berinisiatif membangun 999 masjid di seluruh pelosok Indonesia. Pembangunannya didanai oleh dana zakat para pegawai negeri sipil dan anggota TNI yang disalurkan melalui Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang dibentuknya.
***
Ini semua adalah data dan fakta ‘obyektif’ yang tak bisa dimungkiri oleh semua pihak. Tapi, sekali lagi, masalah utamanya bukan pada data dan fakta ‘obyektif’ itu sendiri, tapi pada subyektivitas penafsirnya. Kalau boleh disederhanakan, titik pijaknya ada pada masalah ‘harga’ yang harus dibayar untuk semua data dan fakta ‘obyektif’ tersebut.
Ambil contoh sederhana, oleh para aktivis pertanian, keberhasilan revolusi hijau harus dibayar dengan ‘harga’ yang mahal. Keberhasilan mencapai swa-sembada pangan, ternyata dibarengi dengan kerusakan tanah akibat penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan. Akibatnya kesuburan tanah turun, struktur tanah rusak, lingkungan tercemar karena residu kimia yang tertinggal. Tanah pun menjadi tidak subur dan memerlukan lebih banyak lagi pupuk serta pestisida kimia untuk dapat memproduksi secara optimal.
Banyak juga kritik yang dilontarkan para ekonom terhadap model ekonomi yang dipilih oleh rezim Soeharto. Mulai dari kegagalan membangun supra dan infrastruktur industri, karena di awal pembangunan terlalu terlena oleh adanya booming harga minyak. Adanya kesenjangan yang lebar antara kaya dan miskin karena pertumbuhan tidak dibarengi pemerataan. Maraknya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagai akibat sistem yang sentralistik. Menurut para ekonom ini, krisis ekonomi 1998 menunjukkan rapuhnya fondasi ekonomi yang dibangun oleh rezim Soeharto.
Untuk masyarakat sipil yang berjuang menegakkan demokrasi dan hak asasi, ‘harga’ yang harus dibayar juga dianggap terlalu mahal. Pemerintahan Soeharto dianggap otoriter dan represif. Kekuasaannya terpusat dan minim mekanisme kontrol terhadap eksekutif. Membungkam kebebasan sipil, termasuk kebebasan pers dan berpendapat, yang membuat perbedaan pendapat sulit disuarakan tanpa konsekuensi.
Tak bisa dipungkiri bahwa pada era Soeharto banyak kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi. Mulai dari tragedi Tanjung Priok, Talangsari, Santa Cruz, status daerah operasi militer di Aceh, penembakan misterius (Petrus), pembunuhan aktivis buruh Marsinah, sampai dengan pembunuhan jurnalis Udin, dan seterusnya.
Sebagian kalangan muslim juga bersuara hampir sama. Ekonomi para saudagar muslim, yang menjadi penopang utama gerakan sosial dan politik mereka, mulai rontok dan menyurut tajam sejak dimulainya rezim Soeharto. Kelompok politik modernis, Masyumi, yang dihabisi di masa Soekarno; dan di awal mendukung Soeharto, tak diberi ruang untuk bangkit kembali. Sementara kekuatan Nahdlatul Ulama (NU) diringkus dan dibonsai dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Meski di akhir kekuasaannya, Soeharto tampak mengakomodasi aspirasi politik ummat Islam lewat pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI); namun sebelumnya dia dinilai hanya mau memfasilitasi muslim kultural dan infrastukturnya saja, sambil secara bersamaan menginjak aspirasi politik mereka.
Tapi, tak boleh dilupakan, banyak juga kalangan aktivis, cendekiawan dan ulama yang dengan satu dan lain cara, dan dengan pertimbangan masing- masing, entah politis mau pun strategis; mendukung sebagian atau keseluruhan, kebijakan yang diambil Soeharto. Salah satu contohnya ada dalam kumpulan esai Abdurrahman Wahid berjudul ‘Kiai Nyentrik Membela Pemerintah’ yang diterbitkan pada tahun 1997. Isinya tentang kiai-kiai, yang bahkan dianggap wali, yang dengan caranya masing- masing mendukung pemerintahan Soeharto.
Jadi, apakah Soeharto memang layak menjadi pahlawan? Pada akhirnya, mengikuti sikap banyak para sufi, tampaknya kita harus membiarkan data dan fakta bebas dibaca orang menurut tafsir subyektifnya masing-masing.
Pemerintah dengan subyektivitasnya sendiri sudah memberinya gelar pahlawan nasional; maka biarkan subyektivitas yang lain menjadi catatan kakinya. Dengan demikian, generasi mendatang bisa memetik pelajaran: kecuali Nabi, tak ada manusia yang sempurna. Sementara makna obyektifnya kita kembalikan pada Allah. Hanya Allah yang tahu nilai sejati di balik semuanya.***