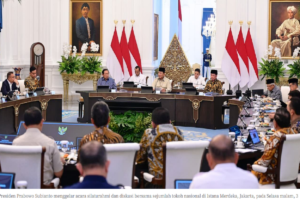Jumlah tersangka menjadi tujuh orang, termasuk empat hakim masuk dalam pusaran kasus itu dan keempatnya telah diberhentikan sementara oleh Mahkamah Agung.
Pengungkapan kasus tersebut segera memperoleh apresiasi dari berbagai kalangan, mulai dari anggota DPR RI, akademisi, penggiat (aktivis), pengamat, dan masyarakat. Kasus ini juga menunjukkan bahwa Reformasi 98 yang mengharamkan Korupsi-Kolusi-Nepotisme (KKN) ternyata masih pada tataran narasi daripada eksekusi.
Korupsi terus terjadi di depan mata publik. Bahkan kini seakan menjadi-jad. Bukan lagi pada angka jutaan, melainkan milyaran bahkan triliunan. Sampai ada yang berseloroh, jika dulu laku suap, sogok, korup secara sembunyi-sembunyi di bawah meja kini terang-terangan dan tanpa malu dilakukan di atas meja bahkan mejanya pun sekalian dikorupsi.
Perlu digaris bawahi bahwa korupsi di lembaga yudikatif akan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap keadilan. Suap yang mengalir di ruang pengadilan adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan konstitusi. Meja hijau bukan lagi menjadi altar keadilan melainkan altar kejahatan.
Celakanya kasus suap, sogok, korupsi sempat terjadi di lembaga peradilan terendah yakni Pengadilan Negeri sampai ke peradilan tertinggi, Mahkamah Agung, meskipun secara fair harus diakui memang masih ada hakim-hakim yang “bersih”. Namun ibarat kata pepatah gegara nila setitik rusak susu sebelanga. .
Jika keadilan bisa dibeli, atribut “Negara Hukum” hanya sampai judul belaka. Kasus semacam ini meskipun bukan baru, sungguh melukai rasa keadilan publik. Benteng keadilan publik runtuh. Penegakan hukum hanya omon-omon.
Hakim adalah sebuah profesi agung dan luhur yang disebut-sebut sebagai pilar keadilan. Sejumlah oknum hakim ternyata runtuh imannya menghadapi godaan suap. Ketika hakim tidak kebal terhadap suap dan sogok, hancurlah benteng keadilan itu sehingga bisa dipahami jika ada pengamat dan ahli hukum yang begitu marah sampai-sampai minta hakim yang korup dituntut hukuman mati
Kemarahan itu bisa dipahami. Mafia peradilan begitu nyata, terang benderang, ceta wela-wela. Tentu saja hukuman, bagaimana pun mesti proporsional, bukan berdasar kemarahan atau balas dendam. Namun penegak hukum yang melanggar hukum memang mesti dihukum lebih berat. Bukan hanya diganjar mutasi. Pasalnya, mereka tahu hukum tetapi “menyiasati” hukum demi memperoleh keuntungan pribadi.
Barangkali bisa disepakati perlu adanya semacam revolusi moral di dunia peradilan terutama lebih selektif dalam merekrut calon-calon hakim. Dicari: hakim yang bukan hanya cerdas dan menguasai hukum, tapi juga berani, bersih, dan tidak tergiur iming-iming uang dan tidak ciut terhadap tekanan kekuasaan.
Komisi Yudisial (KY), sesuai tugas pokok dan fungsinya, semestinya lebih tegas dan awas dalam menyaring calon-calon hakim agar hakim benar-benar sosok berintegritas. Integritas adalah roh seorang hakim. Tanpa integritas, hakim akan terombang-ambing dan berdampak pada hukum yang kehilangan daya dan kepercayaan publik. KY juga lebih efektif dalam melakukan pemantauan terhadap perilaku para hakim demi menjaga marwah profesi tersebut.
Pengawasan publik harus diperkuat antara lain dengan memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pengadilan. Keadilan bukan milik pengadilan, melainkan milik rakyat.
Sejarah keberhasilan beberapa negara memberantas korupsi ditentukan keberhasilan membersihkan korupsi di lembaga peradilan. Maka membangun sistem peradilan yang bersih suatu keharusan. Meskipun demikian perlu disadari membersihkan mafia peradilan adalah sebuah kerja jangka panjang, konsisten, melelahkan dan barangkali disertai kecerewetan, tetapi itu tidak akan pernah terjadi jika tidak memulainya dari sekarang. ***