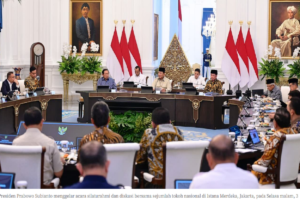Bagi Rustamaji, menjadi dosen bukan pilihan sembarangan. Ia menyebutnya sebagai panggilan hati sejak semester 6 ketika tengah menempuh pendidikan S1 di FH UNS.
Saat itu, di tengah tawaran beasiswa kepolisian dan godaan profesi lain seperti jaksa atau hakim, ia justru memilih jalur pendidikan. Di awal karier, ia sempat ke Jakarta menjadi asisten dosen dan menyusun modul akademik di STIBLAM.
Tahun 2005 ia kembali ke Solo, dan memulai pengabdiannya sebagai dosen hingga kini dipercaya menjabat sebagai dekan FH UNS. “Di dunia akademik, jabatan seperti prodi, wakil dekan, dekan bahkan rektor itu sebenarnya tugas tambahan,” jelasnya.
Hukum dan Moral
Di tengah keresahan publik terhadap lembaga hukum yang sering diwarnai kasus suap dan gratifikasi, Rustamaji menegaskan bahwa Fakultas Hukum UNS tak hanya mendidik mahasiswa dari sisi teknis dan normatif hukum semata, tapi juga secara sadar menyisipkan ajaran etika dan filsafat hukum dalam pembelajaran.
“Hukum itu bukan hanya soal pasal demi pasal. Kita ajarkan bagaimana memahami konteks, nilai moral, dan etika profesi,” ujarnya.
Ia menyebut inspirasi dari pemikiran Paul Scholten maupun Satjipto Rahardjo yang tidak sekadar menekankan kekuatan mengikat teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan nilai kemanusiaan.
“Hakim itu mengenakan pakaian kebesaran, itu soal nilai. Di situ etika berperan besar,” tambahnya.
Menurutnya, gelar “Yang Mulia” pada hakim bukanlah formalitas kosong, melainkan cerminan dari amanah moral yang tinggi. Oleh karena itu, sangat kontradiktif jika hakim atau penegak hukum justru terjerat kasus suap atau korupsi. “Disebut Tuhan di ruang sidang, kok bisa menerima gratifikasi? Itu kontraproduktif.
Kita bekali mahasiswa bukan hanya dengan teori, tapi dengan pemahaman bahwa menjadi penegak hukum itu soal integritas,” tegasnya.
Ladang Perubahan
Di bawah kepemimpinannya, FH UNS terus menumbuhkan model pendidikan hukum yang holistik. Tidak sekadar menghasilkan sarjana hukum, tapi juga membentuk karakter. Rustamaji percaya bahwa pendidikan hukum adalah ladang perubahan sosial.
Bukan hanya mencetak hakim, jaksa, atau pengacara, tapi juga warga negara yang paham hukum dan punya moralitas tinggi. Inilah bekal yang harus dibawa keluar dari kampus.
Dengan pendekatan humanistik dan dialogis, menjadikan ruang kuliah bukan hanya tempat belajar ilmu, tetapi juga ruang penempaan kepribadian. Ia meyakini, jika dunia hukum ingin berubah, maka perubahan itu dimulai dari kampus.
Lupa Tuhan, Lupa Etika
Rustamaji mengkritik fenomena runtuhnya integritas di tubuh aparat hukum, mulai dari jaksa, hakim, hingga advokat, sebagai buah dari satu akar masalah
utama,ketiadaan kesadaran akan kehadiran Tuhan.
Ia mengutip pidato monumental Prof. Barda Nawawi Arief tentang hukum pidana yang bersandar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Prof. Barda menyebut bahwa kejahatan itu tidak ada. Yang ada adalah kondisi ketiadaan Tuhan. Jadi ketika seorang aparat hukum tergelincir, itu karena dia sedang lupa bahwa Tuhan ada bersamanya,” tegasnya.
Baginya, ketika pengadilan hanya menjadi ruang prosedural dan aparat menjadi tukang hukum, yang membacakan pasal tanpa hati nurani, maka saat itulah hukum kehilangan ruhnya.
Ia mengingatkan bahwa banyak putusan hukum hari ini kehilangan substansi keadilan karena terlalu sibuk mengeja bunyi undangundang tanpa menyentuh nilai-nilai etis dan spiritualitasnya.
Dalam sistem pendidikan hukum saat ini, Rustamaji melihat bahwa masih banyak kampus yang menjadikan hukum semata sebagai ilmu positif, teknokratis, tanpa upaya serius menyuntikkan nilai etika yang mendalam.
Ia menyambut baik pendekatan hukum progresif ala Prof. Satjipto Rahardjo yang mengedepankan keadilan dan kemanfaatan dibanding sekadar kepastian normatif.
“Putusan itu harus adil, bukan sekadar sah. Hukum itu harus bernurani, tidak boleh buta terhadap penderitaan rakyat,” katanya.
Ia menekankan bahwa etika profesi bukan sekadar satu mata kuliah dalam kurikulum, tapi seharusnya menjadi nilai hidup yang hadir di semua aspek
pendidikan hukum.
Bukan hanya soal hubungan profesi dengan klien atau sejawat, tapi juga tanggung jawab pada negara dan pada Tuhan. Kalau taat pada undangundang bisa, kenapa pas giliran aturan Tuhan malah diabaikan.
Mengakar Religiusitas
Sebagai pengajar, Rustamaji meyakini bahwa salah satu titik lemah pendidikan hukum di Indonesia adalah kecenderungan memisahkan antara etika dan religiusitas.
Menurutnya, banyak lembaga pendidikan hukum melahirkan “teknisi hukum” yang cakap membaca pasal tapi lemah dalam membedakan baik dan
buruk secara moral.
“Etika dan agama bukan untuk dipisah. Kalau kita percaya pada Pancasila, pada sila pertama, maka semua keadilan harus berangkat dari nilai Ketuhanan. Di setiap judul putusan juga tertulis “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Rustamaji mengajak semua pihak, dosen, mahasiswa, bahkan aparat penegak hukum aktif, untuk menyadari bahwa keadilan tidak bisa dicapai tanpa keikhlasan dan kesadaran spiritual.
Ia menolak keras pendekatan hukum yang steril dari nilai. Hukum bukanlah mesin dingin yang memproduksi putusan, melainkan ruang pertaruhan nilai dan moralitas. Keadilan tidak netral, ia berpihak pada kebenaran. Dan kebenaran itu, dalam hukum yang berjiwa, selalu dimulai dari kesadaran akan Tuhan.
Maka tak mengherankan jika ia menegaskan: Dengan semangat itu, Rustamaji terus menanamkan kepada mahasiswanya, bahwa menjadi penegak hukum bukan hanya profesi, tapi jalan spiritual, jalan perjuangan membela nilai-nilai ilahi di tengah masyarakat yang kadang lupa pada nurani.
Paradoks Pendidikan Hukum
Semakin tinggi pendidikan, seharusnya semakin dalam pula kesadaran etik dan spiritual. Namun yang terjadi di dunia hukum Indonesia hari ini justru memperlihatkan paradoks. Saat gelar akademik para penegak hukum kian tinggi, praktik mafia hukum justru semakin mencoreng wajah keadilan.
Rustamaji memandang fenomena ini sebagai sinyal kegelisahan yang mendalam, bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga para pendidik hukum. Menurutnya, merebaknya pemberitaan tentang mafia peradilan saat ini bukan serta merta menandakan peningkatan jumlah kasus, melainkan karena keterbukaan informasi di era digital.
“Sekarang setiap orang bawa gadget, dan setiap gadget itu kamera, adalah pengawas. Maka semua bisa direkam, difoto, diunggah kapan saja,” ujarnya. Ia menegaskan, ruang pengawasan publik hari ini begitu luas.
Akibatnya, banyak praktik hukum kotor yang dulunya tersembunyi, kini terbongkar dan jadi konsumsi publik. Namun justru karena itulah, kalangan akademisi hukum ikut merasakan kegelisahan kolektif.
“Kita tidak bisa lepas tangan. Sarjana hukum itu produk dari fakultas hukum. Kalau mereka tahu hukum tapi tetap melanggar, justru cara melanggarnya lebih canggih. Ini pisau bermata dua,” tuturnya kritis.
Alat Kejahatan
Rustamaji menyampaikan paradoks menyakitkan:,justru di tengah meningkatnya jumlah penegak hukum bergelar doktor, kasus korupsi, kolusi, dan mafia hukum juga terjadi pada kalangan tersebut. Ini menunjukkan ada ketimpangan antara kedalaman ilmu dan kesadaran moral.
“Harusnya pendidikan itu membesarkan sangkar pengetahuan, dan dari situ muncul kesadaran: ternyata saya kecil, saya tak tahu apa-apa,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kesadaran akan keterbatasan diri adalah puncak dari pendidikan yang benar. Bukan hanya pintar secara teknis, tetapi juga sadar secara etik dan spiritual. Ketika kesadaran itu tidak tumbuh, maka ilmu justru menjadi alat legitimasi kekuasaan atau bahkan kejahatan.
“Kalau orang tahu hukum, tapi tidak punya kesadaran, maka pelanggarannya justru lebih sistemik. Inilah yang membuat kami sebagai pendidik hukum sangat prihatin,” tegasnya.
Berani Berbenah
Rustamaji mengajak seluruh penyelenggara pendidikan hukum untuk tidak sekadar membanggakan gelar atau akreditasi, tetapi mengoreksi kembali substansi pendidikan hukum itu sendiri. Ia menolak pendidikan hukum yang hanya mencetak legal technician, tanpa memperhatikan pembentukan nurani dan karakter.
“Kalau pendidikan tinggi tidak melahirkan integritas, maka itu bukan kemajuan. Itu kemunduran dengan tampilan elitis,” kritiknya.
Ia juga menegaskan bahwa problematika integritas dalam penegakan hukum hari ini bukan sekadar soal kurikulum, tetapi berakar dalam pendekatan terhadap proses pematangan nilai dan karakter, termasuk cara mempersiapkan seorang menjadi hakim, jaksa, atau advokat yang berwibawa dan beretika.
Rustamaji tak menampik bahwa rekrutmen hakim yang berasal dari lulusan sarjana hukum segar memang menyimpan tantangan. Meski secara etik, sarjana hukum telah dianggap sebagai individu otonom, namun ia mengakui pentingnya masa sublimasi nilai yang lebih panjang, seperti yang terjadi di negara-negara dengan sistem kehakiman senioritas.
“Proses pembentukan karakter profesi hukum itu seharusnya tidak berhenti di ruang kuliah. Pendidikan profesi, masa pengabdian, hingga pelatihan etika mesti dilakukan terusmenerus. Konsep belajar sepanjang hayat harus kita tanamkan,” tegasnya.
Perkuat Resistensi Diri Jadilah Figur Teladan
Dalam lanskap hukum Indonesia yang kian sarat tantangan, Dr. M. Rustamaji, SH, MH, mengajukan satu rumus moral. Etika sebaik paduan niat dan kesempatan dibagi Resistensi Diri.
Sebuah formula sederhana namun mengandung kedalaman filsafat moral yang layak direnungkan,terutama oleh para calon penegak hukum yang akan menjadi wajah sistem keadilan Indonesia.
Penyimpangan dalam profesi hukum bukan terjadi karena ketidaktahuan terhadap hukum, melainkan karena lemahnya resistensi etik dan spiritual. Maka, pendidikan hukum tidak boleh sematamata mengejar penguasaan teks dan regulasi, tetapi wajib menanamkan ketangguhan moral.
“Kalau resistensinya lemah, sementara niat dan kesempatan ada, maka penyimpangan pasti terjadi,” tegasnya.
Ia menyoroti pentingnya keteladanan dalam pendidikan hukum. Nama-nama seperti Artidjo Alkostar, Hoegeng Imam Santoso, dan Yap Thiam Hien disebut sebagai cermin ideal dari profesi dan pengabdian hukum yang bersumber dari nurani dan keberanian moral. Membangun figur panutan dari generasi baru adalah tantangan utama ke depan.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada legenda lama. UNS harus melahirkan teladan baru dari barisan mahasiswa dan alumninya sendiri,” ujarnya.
Benteng Terakhir
Rustamaji tidak hanya berbicara pada mahasiswa. Kepada para alumni FH UNS, yang kini banyak mengisi jabatan penting sebagai hakim, jaksa, advokat, hingga birokrat,
ia menitipkan pesan yang tegas namun emosional, jangan lupakan ibu almamater. “Ibu” yang dimaksud bukan sekadar simbol, melainkan almamater,lembaga yang tidak hanya memberi ijazah, tetapi membentuk arah hidup.
“Alumni adalah etalase nyata dari nilai kampus. Kalau satu saja jatuh karena korupsi moral, maka nama baik seluruh keluarga akademik ikut tercoreng,” katanya.
Peringatan ini krusial di tengah maraknya praktik mafia peradilan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat hukum. Alumni bukan sekadar operator hukum, tapi pengarah arah keadilan bangsa.
Maka perilaku mereka, dari ruang sidang hingga ruang rapat, menjadi tolok ukura, pakah pendidikan hukum di UNS berhasil membentuk karakter, atau hanya mengasah keterampilan teknis.
“Jangan gadaikan nama almamater untuk godaan sesaat. Alumni harus menjadi benteng terakhir kepercayaan publik, karena kalau kampus adalah ladang nilai, maka alumni adalah hasil panennya,” jelasnya.