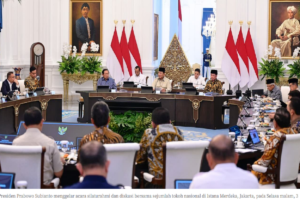Dalam diskusi yang dilakukan oleh KKK MPR RI, putusan ini berpotensi menimbulkan krisis konstitusional. Tobas menyebutkan bahwa sebagai negara hukum, setiap putusan peradilan harus dilaksanakan.
Namun, Putusan MK Nomor 135 menghadirkan dilema. Jika dijalankan, berpotensi melanggar konstitusi, tetapi jika diabaikan, juga bertentangan dengan konstitusi.
Masalah ini bukan hanya soal kepatuhan terhadap MK, tetapi juga terkait kemungkinan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
Putusan MK tersebut menyatakan bahwa Pemilu Nasional untuk memilih DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden harus dipisahkan dari Pemilu Daerah yang memilih DPRD dan kepala daerah. Pemilu Daerah dijadwalkan berlangsung dua hingga dua setengah tahun setelah pelantikan hasil Pemilu Nasional.
Padahal, dalam konstitusi Pasal 22E Ayat 1 dengan tegas disebutkan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
Pasal 22E Ayat 2 menyatakan bahwa pemilu bertujuan memilih DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD. Pasal 18 Ayat 3 juga menegaskan bahwa pemerintahan daerah memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilu.
“Jika amar putusan MK tersebut dimasukkan ke dalam undang-undang, akan muncul pertentangan dengan norma-norma dalam UUD NRI 1945. Inilah inti persoalan yang sedang dikaji lebih dalam,” tegasnya.
Rekomendasi Hasil Kajian
Tobas menyatakan bahwa hasil kajian KKK MPR RI telah disampaikan kepada Ketua MPR, disertai rekomendasi agar MPR mengambil peran strategis terkait Putusan MK Nomor 135.
Meski kini setara dengan lembaga negara lainnya, MPR tetap memiliki keunggulan dalam fungsi dan kewenangan, terutama dalam perubahan dan penetapan konstitusi.
Dengan posisi strategis tersebut, MPR dinilai dapat mengundang lembaga-lembaga negara seperti Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan penyelenggara pemilu untuk bermusyawarah bersama.
“Sesuai dengan nama Majelis Permusyawaratan Rakyat, musyawarah diperlukan untuk mencari jalan keluar dan mencapai konsensus agar putusan MK tetap dapat dilaksanakan tanpa melanggar konstitusi,” ujarnya.
Hasil akhirnya tentu bergantung pada dinamika diskusi yang terjadi. Namun, KKK MPR RI telah menyiapkan sejumlah bahan sebagai substansi pembahasan dalam rapat konsultasi antar lembaga negara.
Salah satu opsi yang diajukan adalah menyatakan putusan MK sebagai non-executable decision, yaitu putusan yang secara konstitusional tidak dapat dilaksanakan sehingga ketidaklaksanaannya tidak dianggap sebagai pelanggaran konstitusi atau ketidakpatuhan terhadap MK.
Alternatif lainnya adalah melaksanakan sebagian isi putusan dengan memilah bagian yang dapat diterapkan tanpa melanggar konstitusi, serta menunda atau menolak bagian yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan konstitusional.
Pilihan lain yang perlu dipertimbangkan adalah kemungkinan perlunya amandemen konstitusi untuk menata ulang desain pemilu secara menyeluruh, mengingat akar persoalan terletak pada norma konstitusi yang tidak membuka ruang untuk itu.
“Bahan-bahan tersebut dapat menjadi substansi dalam rapat konsultasi antar lembaga negara,” jelasnya.
Koridor Konstitusi
Tobas menjelaskan bahwa berdasarkan konstitusi, Pasal 24C menyebutkan negara memiliki MK sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan yang disepakati. Keberadaan MK adalah amanat konstitusi yang harus dijunjung tinggi.
Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai konstitusi. Konstitusi telah membagi kewenangan secara jelas agar kekuasaan tidak menjadi absolut atau otoriter.
Kewenangan pembentukan undang-undang ada pada DPR bersama Presiden, kewenangan mengubah dan menetapkan UUD ada pada MPR, sedangkan kewenangan menguji undang-undang terhadap konstitusi merupakan ranah MK.
Dalam diskusi KKK MPR RI, hal ini dinilai penting untuk dijadikan substansi konsensus bersama.
Prinsip utamanya adalah agar setiap lembaga negara tetap berada dalam koridor kewenangan yang telah ditetapkan oleh konstitusi tanpa saling tumpang tindih.
Hal ini menjadi refleksi bahwa ke depan MK diharapkan bekerja tegas sesuai fungsi konstitusionalnya, yaitu menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD.
Proses perumusan norma tetap menjadi tanggung jawab DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang. “Semoga ada hikmah yang bisa diambil. Polemik ini bisa menjadi momentum untuk meluruskan hal-hal yang mungkin selama ini tumpang tindih,” tambahnya.
Check and Balance
Mengenai kemungkinan bahwa praktik MK dianggap melampaui kewenangannya, salah satu hal yang perlu dibahas adalah komitmen terhadap pelaksanaan konstitusi. Pembagian kekuasaan harus ditegaskan sesuai amanat UUD.
DPR bersama pemerintah adalah pembuat undang-undang, sementara MK berwenang menguji konstitusionalitasnya. Proses legislasi harus dihormati karena didasarkan pada prinsip demokrasi.
Dalam pembuatan undang-undang, DPR dan pemerintah dapat berdiskusi dan mengambil keputusan melalui voting, yang merupakan bagian dari demokrasi. Sebaliknya, MK menjalankan fungsi nomokrasi, menegakkan hukum.
Selama proses demokrasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hukum, negara hukum, dan konstitusi, maka harus dihormati. Namun, jika bertentangan, MK berwenang menyatakan norma tersebut batal atau tidak memiliki kekuatan hukum.
Selanjutnya, pembuat undang-undang harus merumuskan norma baru yang sesuai dengan putusan MK dan tidak lagi melanggar konstitusi. Mekanisme check and balance ini memastikan setiap lembaga bekerja sesuai ranahnya.
Menurut Tobas, secara normatif ketentuan dalam konstitusi sudah cukup jelas, tinggal bagaimana komitmen ini dijalankan. Terkait pemilu sebagai konsekuensi dari putusan MK, wacana amandemen menjadi relevan untuk dibahas, Namun, ia mengaku masih ragu.
“Saya pribadi kurang sreg kalau harus ada amandemen konstitusi hanya karena putusan terkait pemilu. Amandemen seharusnya dilakukan karena persoalan
kebangsaan yang mendasar, bukan karena persoalan teknis dalam satu putusan yang kemudian menimbulkan polemik,” ujarnya.
Harus Ada Jalan Keluar Kebuntuan Konstitusional
Salah satu sumber kebuntuan konstitusional saat ini adalah ketentuan bahwa putusan MK bersifat final and binding. Artinya, putusan MK merupakan keputusan tertinggi yang tidak dapat dikoreksi melalui mekanisme hukum lain.
Ketentuan ini dikhawatirkan dapat menyebabkan masalah serupa di masa depan karena tampaknya tidak ada jalan keluar ketika polemik seperti ini terjadi.
Tobas menjelaskan bahwa dalam teori hukum konstitusi terdapat tiga pandangan besar, yaitu Judicial Supremacy, Departmentalism, dan Popular Constitutionalism.
Dalam model Judicial Supremacy yang berkembang di Amerika Serikat, Mahkamah Agung memegang otoritas tertinggi dalam menafsirkan konstitusi, seperti kasus legendaris Marbury v. Madison tahun 1803.
Namun, Presiden Thomas Jefferson saat itu tidak setuju dan menganut pandangan Departmentalism, di mana setiap cabang kekuasaan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—memiliki hak untuk menafsirkan konstitusi secara independen.
Ada juga Popular Constitutionalism yang menempatkan rakyat sebagai pemilik tafsir tertinggi atas konstitusi. Indonesia sendiri mengadopsi model Mahkamah Konstitusi yang pertama kali diperkenalkan di Austria dan berkembang di Eropa dengan menggabungkan prinsip supremasi yudisial dan pembagian kewenangan antar lembaga negara.
DPR dan Presiden menafsirkan konstitusi dalam proses legislasi, pemerintah melalui kebijakan eksekutif, dan MK dalam pengujian undang-undang terhadap UUD.
Permasalahan muncul ketika MK tidak hanya menguji norma hukum tetapi juga mengunci norma teknis dalam amar putusan. Contohnya, dalam Putusan 135, MK menetapkan Pemilu Nasional dan Daerah harus dipisahkan dengan jeda dua hingga dua setengah tahun, yang mengunci desain teknis pemilu.
Putusan seharusnya bersifat final pada aspek konstitusionalitas, bukan aspek teknis. Ketika amar putusan mengunci norma, ruang diskusi legislasi tertutup dan berpotensi melanggar prinsip pemisahan kekuasaan.
“Seandainya Putusan 135 hanya memuat pertimbangan umum seperti efisiensi dan kualitas demokrasi tanpa mengunci desain teknis, polemik ini tidak akan terjadi,” ujarnya.
Jalan Tengah
Ada banyak solusi, misalnya seperti usulan Prof. Mahfud MD, adalah pemilu sela untuk DPRD, di mana pemilihan berlaku dua hingga dua setengah tahun, lalu diselenggarakan kembali agar sesuai dengan Putusan MK.
Usulan ini dapat diatur melalui undang-undang khusus. Pandangan ini sejalan dengan Tobas, yang menilai Putusan MK 135 dilematis karena berpotensi bertentangan dengan UUD, namun tetap harus dilaksanakan. Tobas menyarankan pemilu sela dipertimbangkan dalam pembahasan DPR dan pemerintah.
Namun, ada hal lain yang perlu diperhatikan. Usulan seperti ini harus dicermati karena amar Putusan MK telah mengunci rumusan normanya. Amar putusan tersebut mirip dengan teks undang-undang yang harus diikuti secara tepat.
Namun, usulan pemilu sela tidak sepenuhnya sesuai dengan isi amar tersebut, sehingga ruang untuk mengimplementasikan alternatif seperti ini menjadi terbatas. Jika diterapkan, konsekuensinya adalah penyelenggaraan dua kali pemilu dalam lima tahun, yang memerlukan kajian mendalam.
“Berbagai opsi perlu dibuka dan didiskusikan selama tetap berada dalam koridor konstitusi. Prinsip utamanya adalah menjaga agar proses tetap sejalan dengan norma dasar ketatanegaraan,” ujarnya.
Revisi UU MK
Tobas, yang telah lama berada di DPR RI, mencatat bahwa Undang-Undang MK telah mengalami beberapa perubahan, khususnya terkait periodisasi. Awalnya, masa jabatan hakim MK adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali.
Berdasarkan putusan MK, hakim yang maju untuk periode kedua tidak perlu melalui proses administrasi dari awal, meskipun masa jabatan tetap lima tahun.
Kemudian, revisi mengubah sistem periodisasi menjadi pengabdian hingga masa pensiun, yaitu sampai usia 70 tahun. Setelah terpilih, hakim menjabat hingga masa tugasnya selesai. Pada periode lalu, sempat ada diskusi untuk mengembalikan sistem ke periodisasi.
Ada juga gagasan agar setelah satu periode selesai, dilakukan evaluasi terhadap hakim MK untuk menentukan kelanjutan jabatannya. Ini mirip dengan sistem periodisasi lama, hanya berbeda pada mekanisme seleksi ulang atau evaluasi.
Namun, jika usulan revisi diajukan saat situasi sedang ramai, wajar jika muncul kecurigaan. Karena itu, sebaiknya fokus diarahkan pada penyelesaian persoalan pelaksanaan putusan MK terlebih dahulu.
Dengan begitu, jika revisi diperlukan nantinya, tidak muncul kesan balas dendam atau motif politik, yang tidak baik dalam proses bernegara.
“Sebaiknya, fokus diarahkan pada penyelesaian masalah pemilu, dan setelah urusan pelaksanaan putusan MK selesai, barulah pembahasan revisi Undang-Undang MK dilakukan,” katanya.
MPR memiliki posisi strategis untuk menyelesaikan situasi ini, yang hampir menjadi krisis Undang-Undang Dasar dan ketatanegaraan. MPR dapat mengambil inisiatif untuk mempertemukan lembaga-lembaga tinggi negara dan menyepakati langkah terbaik berdasarkan putusan MK.
“Yang terpenting adalah mencari jalan keluar dan tidak berhenti di tengah-tengah polemik, karena akan sangat disayangkan jika bangsa ini terjebak dalam kebuntuan politik yang berkepanjangan,” tutupnya.