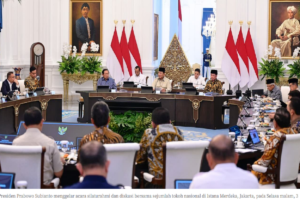Memasuki 2026, kita perlu sungguh-sungguh merefleksikan dinamika hukum pemilu yang terjadi sepanjang 2025. Tahun 2025 mencatat bahwa reformasi hukum pemilu lebih banyak berjalan melalui jalur yudisial di Mahkamah Konstitusi (MK), ketimbang melewati proses legislasi di DPR sebagaimana idealnya.
Fenomena itu harus dipahami secara utuh, bukan sebatas persoalan, tapi juga respons atas kondisi hukum pemilu Indonesia saat ini. Sepanjang 2025, MK telah menghasilkan banyak putusan penting (landmark) terkait pengaturan pemilu.
Mulai dari Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 terkait penghapusan ambang batas pencalonan presiden; Putusan No. 121/PUU-XXII/2024 terkait keberadaan lembaga independen pengawas sistem merit aparatur sipil negara (ASN);
Putusan No. 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah; Putusan No. 169/PUU-XXII/2024 terkait keterwakilan perempuan di keanggotaan dan pimpinan alat kelengkapan DPR;
hingga Putusan No. 104/PUU-XXIII/2025 terkait penegasan pilkada sebagai pemilu, sehingga produk hukum penanganan pelanggaran administratif Bawaslu adalah berupa putusan, bukan lagi rekomendasi.
Aktivisme MK
Sebagian besar putusan landmark MK di isu kepemiluan tidak memiliki dissenting opinion atau pendapat berbeda di antara majelis hakim yang memutus perkara.
Hal itu setidaknya menunjukkan adanya kesepahaman hakim dalam membaca aspek konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya. Ditambah dengan puluhan putusan sengketa hasil Pilkada 2024 yang ikut memberikan arah baru pengaturan hukum pilkada,
maka MK makin jadi rujukan utama sekaligus menegaskan eksistensinya sebagai pengadilan pemilu (election court) di Indonesia.
Dalam hal ini, peran aktif MK perlu dipahami sebagai respons atas situasi legislasi parlemen yang tidak adaptif terhadap kebutuhan dan aspirasi publik atas pembaruan hukum pemilu.
DPR lamban dan tidak proaktif dalam menyusun dan membahas RUU Pemilu, padahal dialektika tentang kepastian dan konstitusionalitas norma pemilu masih sangat kuat di tengah masyarakat.
Akhirnya, MK dijadikan tumpuan utama publik untuk mengisi kekosongan itu melalui putusan-putusan yudisialnya. Apalagi faktanya, meskipun RUU Pemilu merupakan RUU prioritas Prolegnas 2025 usulan dari Badan Legislasi DPR,
namun sampai dengan berakhirnya tahun 2025, belum ada keluaran konkret berupa Naskah Akademik maupun Draf RUU Pemilu yang dihasilkan DPR.
melainkan bentuk pelaksanaan fungsi konstitusional MK sebagai penjaga konstitusi dan pengawal hak konstitusional warga negara. Publik yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar memiliki akses ke MK, dan MK merespons dengan memberikan putusan yang berbasis konstitusi dan penegakan nilai-nilai demokrasi.
MK yang seharusnya menjadi pengawal akhir konstitusi, kini harus mengambil peran lebih besar dalam mengisi kekosongan normatif hukum pemilu. Masyarakat sipil dan pengadilan kemudian menjadi pendorong utama reformasi pemilu Indonesia (main electoral reform driver).
Padahal, sudah semestinya inisiatif reformasi datang dari parlemen. Hal yang mengkhawatirkan dari fenomena ini adalah munculnya ketergantungan sistemik pada jalur yudisial untuk reformasi pemilu. Publik menjadi lebih percaya mengajukan gugatan ke MK, dibanding menyampaikan aspirasi ke DPR.
Kondisi itu sejatinya mencerminkan krisis kepercayaan yang makin besar terhadap legislatif dan proses legislasi. Eksesnya, sejumlah elite politik secara terbuka mulai mempersoalkan putusan MK, terutama terkait pemisahan pemilu serentak nasional dan daerah.
Namun, anomali dan ironisnya, keberatan dan protes itu tidak diikuti dengan upaya serius untuk menghasilkan undang-undang yang lebih baik dan responsif.
Bahkan yang muncul justru wacana untuk mengembalikan pilkada ke DPRD. Gagasan yang jauh mundur dari perkembangan desain demokrasi konstitusional Indonesia, yang saat ini mulai ajeg.
Konstitusionalitas Pilkada
Di tengah berbagai dinamika hukum pemilu, perdebatan tentang pilkada langsung versus tidak langsung menguat di penghujung 2025. Namun, perdebatan ini sebenarnya secara konsisten sudah dijawab terang benderang oleh konstitusi dan yurisprudensi MK.
Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Terkait hal itu, MK telah memberikan penafsiran yang sangat jelas tentang makna “dipilih secara demokratis” tersebut.
Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 menekankan pentingnya stabilitas sistem pemilu. MK menyatakan bahwa tidak boleh terlalu sering mengubah model pemilihan langsung yang sudah berjalan serentak, agar terbangun kepastian hukum dan kemapanan pelaksanaan.
Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 kemudian menegaskan eksplisit bahwa pilkada adalah bagian dari pemilu, setelah beberapa periode pilkada langsung dilaksanakan secara konsisten dan menemukan bentuk terbaiknya.
Oleh karena itu sengketa hasil pilkada tetap diselesaikan MK, dan bukan oleh Badan Peradilan Khusus Pilkada.
Terakhir, Putusan MK No. 110/PUU-XXIII/2025 yang memberikan pertimbangan hukum terang benderang. MK menyatakan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Karena itu, Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 harus berlaku sama untuk pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pilkada. Ini bukan putusan yang mengada-ada atau melampaui batas, tetapi pembacaan konsisten terhadap konstitusi dan praktik ketatanegaraan yang telah berjalan.
Pilkada langsung juga didukung oleh berbagai pertimbangan yang saling menguatkan. Dari aspek historis, pilkada langsung adalah hasil perjuangan panjang menuju demokrasi lokal yang partisipatif pasca-Orde Baru.
Dari aspek politik, ini merupakan kompromi politik pascareformasi yang telah teruji melalui beberapa siklus pemilihan sejak 2005. Dari aspek sosial, masyarakat telah ikut berpartisipasi dan terlibat dalam pilkada langsung sebagai wujud kedaulatan rakyat di tingkat lokal.
Dari aspek konsolidasi demokrasi, pilkada langsung terbukti memperkuat legitimasi kepala daerah dan memperdalam internalisasi demokrasi lokal. Dari aspek konstitusionalitas, pilkada langsung adalah amanat konstitusi yang harus dihormati.
Lebih dari itu, pilkada menjadi sarana mengelola konflik politik sekaligus membangun kohesi sosial melalui kompetisi yang terlembaga.
Tentu saja, pilkada langsung tidak sempurna. Berbagai putusan MK dalam sengketa Pilkada 2024 mengungkap sejumlah masalah yang harus serius diperbaiki.
Mulai dari masalah politik biaya tinggi yang terjadi secara tersembunyi, membuat calon berkualitas tanpa kekuatan modal besar sulit untuk berkompetisi secara setara. Problem netralitas ASN dan kepala desa yang jadi momok karena banyak dipolitisasi atau terlibat memobilisasi dukungan untuk kontestan tertentu.
Politik uang dan jual beli suara masih terus terjadi dan kian merusak integritas kompetisi. Pencalonan yang tersentralisasi dan praktik mahar politik amat membebani calon.
Padahal, desentralisasi politik justru seharusnya diperkuat sebagai arena promosi kader terbaik partai di tingkat kontestasi lokal. Selain itu, masih terjadi manipulasi suara dalam berbagai tahapan,
mulai dari penghitungan hingga rekapitulasi, yang mendistorsi kemurnian suara pemilih. Serta, netralitas penyelenggara pemilu yang problematik juga ikut mendegradasi kredibilitas pilkada.
Saat ini yang dibutuhkan adalah evaluasi menyeluruh dan komitmen perbaikan pilkada yang dilakukan konsisten. Bukan sebaliknya, mengubah sistem pemilihan langsung yang sejatinya sudah terlembaga secara konstitusional.
Reformasi Hukum Pemilu
Memasuki 2026, paling tidak ada sejumlah agenda reformasi yang perlu dikerjakan bersamaan untuk memperbaiki sistem pemilu Indonesia. Pertama, memastikan segera dilakukannya kodifikasi pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah UU Pemilu.
Saat ini pengaturan terpecah dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. Fragmentasi ini menciptakan inkonsistensi dan celah hukum yang berdampak ketidakpastian penyelenggaraan pemilu dan pilkada.
Dengan menyatukan semuanya dalam satu kitab undang-undang hukum pemilu, maka akan lebih mampu menjamin konsistensi, memudahkan implementasi, dan mengurangi potensi sengketa.
Kedua, urgensi reformasi partai politik melalui revisi UU Partai Politik. Hal ini mendesak dilakukan mengingat partai politik ikut menjadi bagian dari hulu banyak persoalan pemilu Indonesia.
Jika partai tidak direformasi sejalan upaya reformasi hukum pemilu, maka perbaikan sistem pemilu hanya akan jadi kerja parsial dan tidak sepenuhnya mampu menjawab permasalahan yang ada.
Terkait itu, dalam revisi UU Partai Politik perlu memasukkan pengaturan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), memperkuat desentralisasi politik, dan mengembalikan kedaulatan partai kepada anggota.
Ketiga, reformasi pendanaan politik dengan meningkatkan alokasi dana negara untuk partai politik agar lebih mampu menopang fungsi dan tata kelola internal yang kredibel dan modern.
Dana tersebut harus digunakan untuk kaderisasi yang berkualitas, rekrutmen politik melalui pemilihan internal (primary election) yang demokratis, dan mensyaratkan masa keanggotaan minimal untuk pengisian jabatan politik.
Dengan pendanaan negara yang memadai, partai tidak perlu bergantung pada pemodal dan sumber dana yang tidak jelas. Dampaknya, pintu masuk politik bisa lebih terbuka dan aksesibel untuk lebih banyak orang.
Keempat, pengesahan UU Pembatasan Transaksi Tunai/Uang Kartal sebagai upaya integral mewujudkan integritas dana politik. Dengan membatasi transaksi tunai di atas jumlah tertentu,
akan ada jejak digital yang memudahkan pelacakan praktik politik uang dan aktivitas transaksional lainnya. Pengalaman dari banyak negara, digitalisasi transaksi keuangan bisa efektif mengurangi praktik lancung politik uang.
Sebagai penutup, tahun 2026 seharusnya jadi momentum yang tidak bangsa ini lewatkan untuk melakukan aksi nyata bagi reformasi hukum pemilu. Kita sudah cukup lama berkutat dengan masalah yang sama dan itu-itu saja
Bukan karena tidak tahu apa solusinya, tapi karena pragmatisme partisan yang terlalu kuat mencengkeram terwujudnya perbaikan.
*) Titi Anggraini, Pengajar Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Sumber : HukumOnline.com