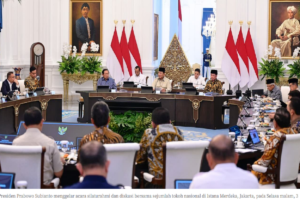Pada awal 1980-an, Bambang Sadono (BS) menjadi redaktur Rubrik Budaya di Minggu Ini Suara Merdeka yang terbit seminggu sekali. Saat itu, BS bersama kawan-kawannya membentuk organisasi kepenulisan Keluarga Penulis Semarang (KPS).
Ada pameo bahwa tulisan dari penulis luar Semarang sulit dimuat di Suara Merdeka, karena Rubrik Budaya didominasi penulis Semarang, khususnya yang aktif di KPS.
Seperti saya, meski sering mengirim tulisan dan kerap dimuat di mingguan Dharma, Kartika, dan media lain, tak pernah sekalipun dimuat di Suara Merdeka. Namun, anggapan dominasi KPS itu ternyata keliru.
Saat saya mengirim puisi “Seorang Kakek Bersurban di Surau dengan Cucunya” dengan nama Lis Nurhayati (pacar saya kala itu), puisi tersebut dimuat pada edisi 3 Juli 1983. Saya geli, tertawa, sekaligus menyesal telah mencurigai BS.
Lahir di kota kecil jauh dari Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, sejak kecil BS sudah “kasinungan wahyu”, nalurinya mengalir menuntut ilmu mencari jati diri.
Layaknya kisah Brotoseno yang lahir dalam “bungkus” dan dibebaskan oleh gading Gajah Seno, “bungkus” BS dipecahkan oleh semangat dan cita-citanya untuk meraih ilmu dan keluar dari kotanya.
Ilmu Kehidupan
Di perantauan, perjuangan BS tak hanya menuntut ilmu formal, tetapi juga menyerap ilmu kehidupan dari segala penjuru angin. Ia tak pernah gentar menghadapi rintangan karena memegang teguh filsafat angin (bayu) yang mampu menyusup ke setiap ruang dan tempat.
Brotoseno (Bayu Mangkurat) bersahabat dengan Anoman (Bayu Kiran), Ditya Jajakwreka (Bayu Anras), Resi Maenaka (Bayu Langgeng), Liman Situbana (Bayu Kanetra), Naga Kuwera, Garuda Mahambira, dan Macan Palguna.
Mereka, sesama Bayu, adalah rekan seperguruan yang menimba ilmu dari Batara Bayu. Mereka adalah “sedulur sinoroh wadi” bagi Brotoseno, yang berkat dukungan mereka berhasil lulus dari segala ujian.
BS telah meraih predikat “sarjana”, namun masih harus menempuh perjalanan menuju predikat “sujana” demi mencapai jati dirinya. Memasuki proses berikutnya,BS mulai menjelajahi keragaman kehidupan.
Kaidah sastra yang sudah menyatu dalam dirinya berpadu dengan nilai budaya. Belantara kehidupan ia masuki penuh perjuangan dan pencarian makna.
Perpindahan tempat, ideologi, maupun prinsip menjadi bagian dari pencariannya. Brotoseno akhirnya menjelma menjadi Bima. Ia menaklukkan hutan belantara yang lebat dan angker,
Wanamarta, melawan segala rintangan, memahami watak kehidupan, hingga pada puncaknya mampu membangun kerajaan Amarta bersama pendampingnya, Dewi Arimbi, yang kelak melahirkan “wiji pinilih” penerus sejarahnya.
Bima Suci
Namun, kepuasan tak pernah terlintas di benaknya. BS telah mampu meraih nilai kehidupan, dengan karakter yang hanya berhenti ketika raga tak lagi bergerak.
Seperti Bima, yang tak berhenti mencari jati diri dan hakikat hidup. Pelajaran dari gurunya, Druna, menjadi obsesi untuk menemukan “sejatining urip”. Bima telah “sembada” menaklukkan segala nafsu dalam dirinya. Nafsu Sufiah dan Amarah ia redam saat “membunuh” dua raksasa,
Rukmuka yang berkulit kuning dan Rukmakala yang berwarna merah di gunung Candramuka. Aluamah, yang berwujud keinginan duniawi, berhasil ia kendalikan ketika mengabaikan larangan keluarganya, termasuk ibunya,
Dewi Kunti, untuk terjun ke samudra. Terakhir, Bima mampu mengalahkan naga besar dan mengarahkan nafsu mutmainah yang putih menuju “sembah jiwa” kepada Gusti Allah.
BS juga berhasil memetik inti sari religiusitasnya, konsisten dan khusyuk menjalankan aturan agama. Lima aji utama telah dilaksanakan dengan sepenuh jiwa raga, menjadikan predikat “waskita” seharusnya menyatu dalam dirinya.
Kewajiban terakhirnya adalah mengamalkan kebijaksanaan kepada “sesaming tumitah ing alam donya”. Bima telah menuntaskan kewajiban spiritualnya dan bergelar Bima Suci.
Meski tak lagi aktif langsung di dunia kesenian, salah satu bidang yang membesarkannya, BS tetap peduli memajukan kesenian di Jawa Tengah, khususnya. Ia kerap membantu kegiatan Dewan Kesenian Salatiga, bahkan mendorong perjuangan adanya peraturan daerah untuk melindungi kesenian.
Sebagai penutup, berikut puisi berbahasa Jawa karya Bambang Sadono SY, yang mungkin sudah ia lupakan pernah dibuat.
KANGEN
(kanggo Sudharmo K.D.)
aku kelingan sliramu kanthi geter pater ing atiku
nalika kokelus pundhakku
“kene, cah bagus dakwacakake guritanmu”
kandhamu kanthi esem kang biru
akh, 1980 wis mungkur lakon terus owah gingsir kumitir
adoh, nglangut, nyamut-nyamut nanging
mripatmu kok tinggal ing kene ing latar kang kelebu cengkar
aku kelingan sliramu
nanging klaten, sala lan semarang wis ora bisa ketemu
mung ing gelenging tekad anteping ati
keblatmu bakal dakluru.