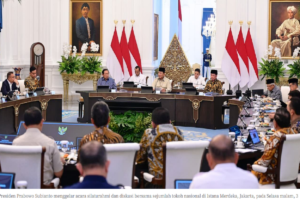Ia bukan pemimpin orator seperti Sukarno, bukan pula ideolog revolusioner. Ia lebih mirip petani yang menanam kekuasaan perlahan, sabar, dan penuh perhitungan. Dalam dirinya, politik berpadu dengan rasa Jawa: eling lan waspada, menang tanpa ngasorake, dan tapa ngrame.
Soeharto bukan sekadar kepala negara, melainkan cermin bagaimana kebudayaan Jawa membentuk, sekaligus membatasi kekuasaan. Dalam berbagai forum, ia sering bicara, “Aja rumangsa bisa, nanging bisaa rumangsa.”
Banyak Mendengar
Soeharto lahir pada 8 Juni 1921. Hidup di tengah masyarakat agraris, ia belajar nilai-nilai utama budaya Jawa, antara lain rukun, hormat, sabar, narima, alon- alon waton kelakon. Sejak muda, ia lebih senang bekerja dalam diam.
David Jenkins dalam Young Soeharto: The Making of a Soldier (1921–1945) (ISEAS, 2023) menggambarkannya sebagai sosok yang “lebih banyak mendengar daripada berbicara.” Ia bukan tokoh ideolog, melainkan pengamat tajam yang memandang politik sebagai seni menata keseimbangan.
Ketika bergabung dengan KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda, lalu PETA (Pembela Tanah Air), hingga Tentara Nasional Indonesia (TNI), ia mengasah kedisiplinan dan naluri strategis. Dalam perang kemerdekaan, Soeharto jarang tampil di depan, tapi langkahnya menentukan. Dalam filosofi Jawa, itulah tapa ngrame: kesunyian yang bekerja dalam keramaian.
Peristiwa 30 September 1965 menjadi panggung peralihan sejarah. Di tengah kekacauan nasional, Soeharto tampil. Ia mengambil alih kendali militer, lalu politik, dan akhirnya kekuasaan nasional. R.E. Elson menulis dalam Suharto: A Political Biography (2001), “Ia tidak merebut kekuasaan dengan kekerasan, melainkan dengan kesunyian yang strategis.”
Bagi orang Jawa, langkah itu sejalan dengan laku menang tanpa ngasorake, menang tanpa harus mengalahkan secara terbuka. Sejak itulah, Soeharto memulai babak panjang Orde Baru, dengan tekad membangun bangsa melalui ketertiban dan pembangunan.
Stabilitas Politik
Pada akhir 1960-an, Soeharto membangun tatanan baru dengan dua sayap utama, yaitu stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Bersama teknokrat, seperti Widjojo Nitisastro dan Emil Salim, ia merumuskan strategi pembangunan yang menekankan pertumbuhan dan disiplin fiskal.
Hasilnya cepat terasa. Indonesia mencapai swasembada pangan, menurunkan angka kemiskinan dari 70% menjadi 11%, dan mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun (World Bank, 1998). Soeharto pun mendapat pengakuan dunia. Pada 8 Juni 1989, di markas besar PBB, New York, ia menerima UN Population Award.
Dalam pidatonya, ia menegaskan: “Masalah kependudukan adalah masalah sentral dalam pembangunan nasional. Keberhasilan KB bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang kualitas manusia.”
Bagi Soeharto, pembangunan bukan sekadar ekonomi, melainkan tata nilai; membentuk keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Dalam kacamata Jawa, ini adalah bentuk ngayomi: melindungi rakyat seperti seorang bapak menjaga anak-anaknya.
Soeharto dicitrakan sebagai “Bapak Pembangunan”, namun tersimpan paradoks di balik citra tersebut. Demokrasi dibatasi dengan dalih stabilitas. Partai politik disederhanakan, pers dibungkam, dan kekuasaan dipusatkan. “Demokrasi Pancasila” menjadi nama indah bagi sistem politik paternalistik yakni demokrasi yang dikendalikan agar tetap rukun.
Konsep Demokrasi
Dalam penerbangan New York-Geneva-Jakarta, pulang dari markas PBB itu, saya sempat bertanya kepada Pak Harto tentang demokratisasi.
“Demokrasi belum bisa kita terapkan secara penuh, karena masyarakat belum siap. Demokrasi itu ibarat kran air, membukanya harus pelan-pelan, bertahap. Jangan sampai kebablasen,” jawabnya.
Dalam kebudayaan Jawa, kekuasaan sering diibaratkan rumah tangga besar. Negara adalah keluarga, presiden adalah bapak, dan rakyat adalah anak-anak yang harus manut agar tentrem. Tapi harmoni yang dipaksakan sering berujung pada ketakutan.
Retnowati Abdulgani-Knapp dalam Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia’s Second President (2007) mencatat, sistem patronase yang lahir dari relasi bapak- anak buah akhirnya menciptakan lingkaran kroni dan korupsi.
Nilai rukun berubah menjadi alat legitimasi, ajining panguwasa (kehormatan penguasa) bergeser menjadi tameng kekuasaan. Seperti dalam lakon wayang, sang raja terlalu lama berkuasa hingga lupa pada bayangannya sendiri.
Lengser keprabon
Krisis moneter 1997 menjadi badai yang mengguncang Orde Baru. Nilai rupiah runtuh, harga bahan pokok melonjak, dan mahasiswa memenuhi jalan-jalan menuntut reformasi.
Harold Crouch menyebut peristiwa itu sebagai “momen kehancuran legitimasi moral” (The Army and Politics in Indonesia, 1999).
Pada tahun itu, saya menjadi koresponden The Courier Mail, koran milik konglomerat media Rupert Murdoch, yang terbit di Brisbane, Australia. Reportase utama saya adalah mengupas dan mengkaji kondisi sosial-politik saat-saat Soeharto lengser.
Kemis Legi, tanggal 21 Mei 1998, Soeharto lengser keprabon; istilah Jawa yang berarti turun tahta dengan kesadaran. Ia meninggalkan Istana tanpa kemarahan. Wajahnya tenang, langkahnya pelan, seolah memahami bahwa waktu telah menutup daurnya. Namun, bayangannya tidak pernah hilang dari politik Indonesia. Ia meninggalkan warisan ganda: kemajuan ekonomi sekaligus ketimpangan sosial, ketertiban sekaligus pembungkaman.
Dalam Serat Kalatidha karya Ranggawarsita, digambarkan bahwa setiap zaman akan mengalami prahara sebelum lahirnya keseimbangan baru. Kejatuhan Soeharto adalah bagian dari siklus itu — tumimbal balik zaman, ketika harmoni harus ditebus dengan perubahan.
Soeharto wafat pada 27 Januari 2008, tapi spirit kepemimpinannya masih terasa hingga kini: sabar, halus, dan paternal. Banyak politisi modern masih meniru gayanya; tenang di permukaan, namun mengatur arus di bawah. Ia telah menjadi arketipe: pemimpin Jawa modern yang memadukan keratonisme dan kalkulasi politik.
Paradoks Paripurna
Secara kultural, Soeharto bisa dibaca sebagai manusia paripurna dalam paradoks: membangun sambil membatasi, menyatukan sambil menundukkan, dan memimpin dengan diam. Setelah lengser, ia memilih berdiam; tapa brata seorang raja tua yang tahu kapan berhenti.
Biografi politik Soeharto adalah cermin tentang bagaimana budaya membentuk kekuasaan. Dalam dirinya, kita melihat perpaduan antara spiritualitas Jawa dan realpolitik modern. Ia membangun negara seperti menata rumah: rapi, teratur, tapi menuntut kepatuhan.
Soeharto telah pergi, namun bayangannya tetap menjadi peringatan bagi setiap pemimpin. Bahwa kekuasaan tanpa koreksi melahirkan keangkuhan, dan pembangunan tanpa kebebasan menumbuhkan kerapuhan.
Pertanyaannya kini, apakah bangsa ini masih mencari “bapak” yang bisa menjaga harmoni, atau sudah siap menjadi rakyat yang dewasa dalam kebebasan?
Penulis: Dr. Adi Ekopriyono, MSi – jurnalis senior, Direktur PT Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Semarang, USM LCC.