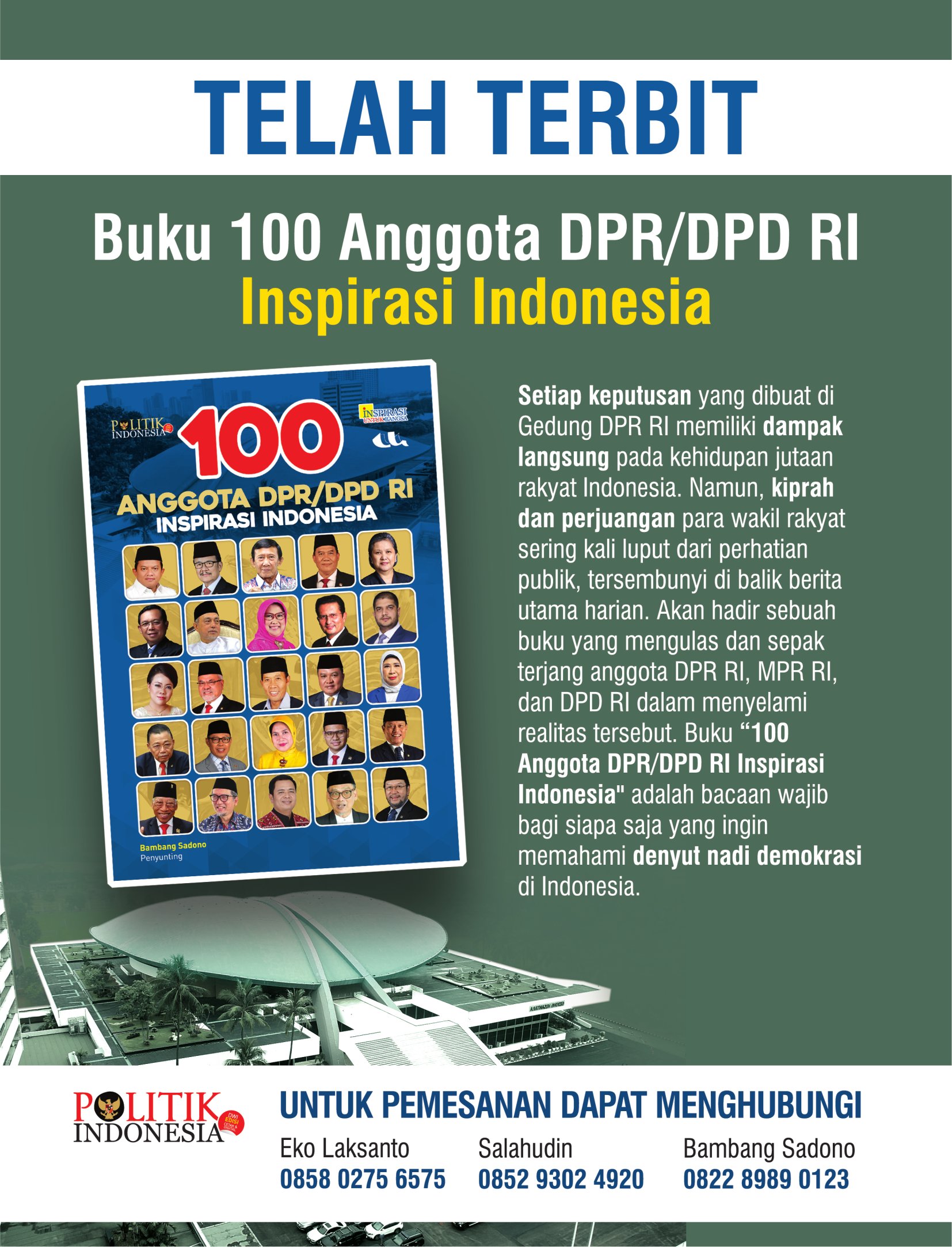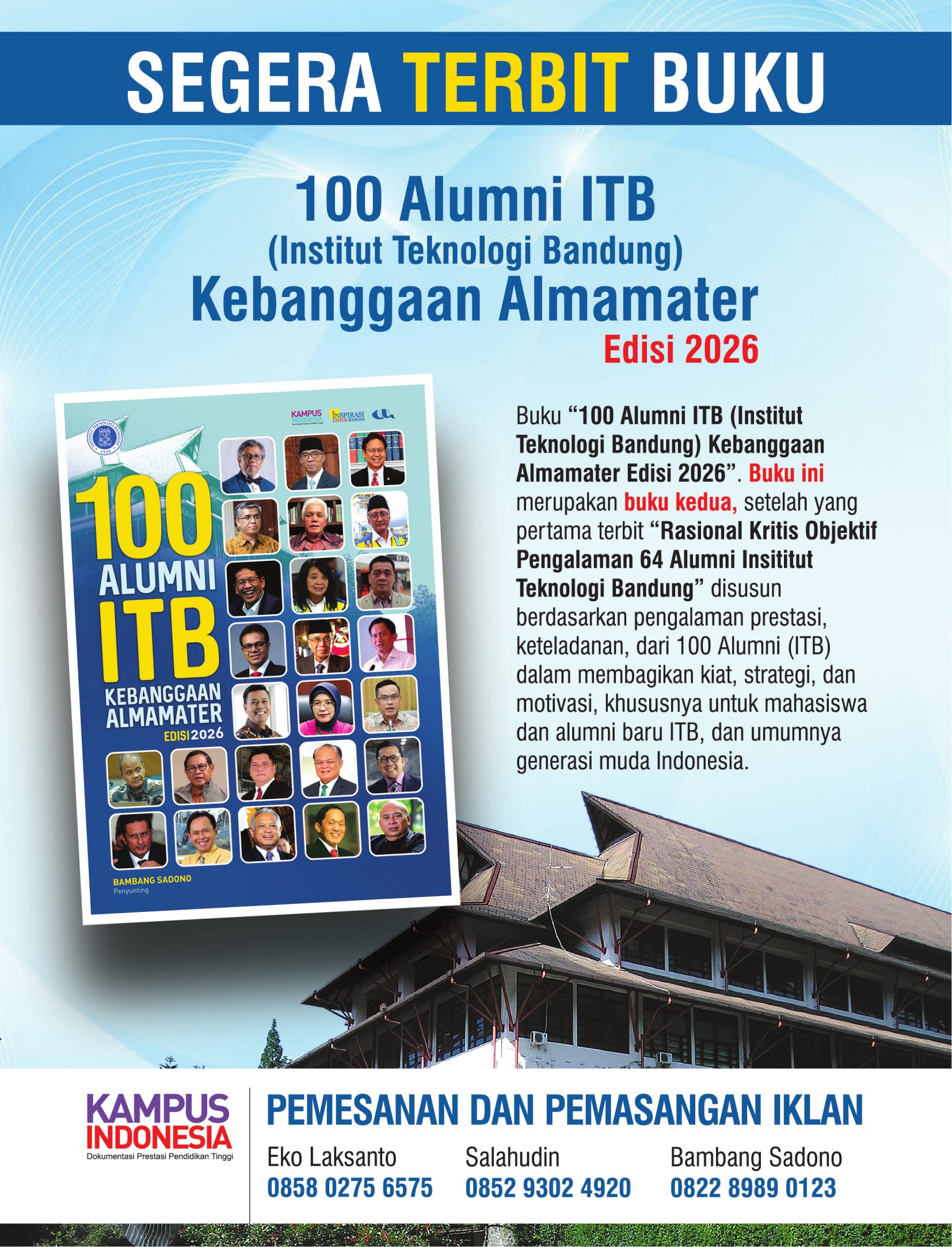kondisi seperti ini, bukan hanya volume air yang meningkat, tetapi juga kecepatannya. Air tidak lagi meresap—ia menerjang, menyeret tanah, batu, dan rumah di hadapannya. Semua itu bukan keputusan alam, melainkan keputusan manusia yang dilegalkan oleh kebijakan dan diamnya para pemegang kekuasaan.
Bencana besar di Sumatra bukan sekadar cerita tentang hujan ekstrem. Ini adalah cerita tentang catatan alam, mengenai setiap pohon terakhir yang ditebang, setiap lereng yang dikupas, dan setiap sungai yang dipersempit demi kepentingan jangka pendek. Ketika badai datang, seluruh catatan itu disajikan kembali dalam bentuk banjir bandang, longsor beruntun, dan ribuan keluarga kehilangan rumah.
Namun ada satu rangkaian catatan yang tak boleh dihapus, peran politisi, keserakahan, kelalaian, dan keacuhan sistematis yang ikut membentuk lanskap bencana dalam wujud nyata kebijakan “ekonomi-serakah” atau “serakah- nomics”, meminjam istilah Presiden Prabowo.
Keputusan Politik
Tidak ada longsor besar yang terjadi tiba-tiba. Tidak ada banjir bandang yang lahir dari satu malam. Bencana adalah akumulasi keputusan politik selama bertahun-tahun. Penyebabnya antara lain perizinan yang dikeluarkan dengan mudah dan didasarkan kolusi. Juga pengawasan yang dibiarkan tumpul.
Sementara Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang hanya formalitas. Ada janji kampanye yang bersandar pada rente sumber daya alam. Ditambah legislasi yang ditafsirkan untuk menguntungkan kelompok kecil, bukan keselamatan publik.
Dalam banyak kasus, bukit-bukit digerus bukan karena kebutuhan rakyat, melainkan karena kekuatan modal yang bersahabat dengan kekuasaan. Sungai-sungai dipersempit bukan karena ketidaktahuan teknis, tetapi karena keputusan politik yang memilih menutup mata.
Keserakahan sebagian elit tidak selalu hadir dalam bentuk korupsi uang tunai; sering kali ia hadir dalam bentuk pembiaran, penundaan pengawasan, atau diam yang disengaja ketika izin bermasalah diberikan.
Ekonomi Jangka Pendek
Politisi sering menggunakan narasi “pembangunan” untuk membenarkan pembukaan lahan atau izin eksploitasi. Tetapi setelah bencana, terlihat sangat jelas bahwa nilai ekonomi jangka pendek itu tidak sebanding dengan kerugian yang sekarang harus ditanggung masyarakat.
Jadilah embatan dan jalan hancur, jaringan listrik terputus, ribuan rumah lenyap, produktivitas wilayah turun drastic, dan anggaran negara terkuras untuk pemulihan yang seharusnya tidak perlu terjadi.
Ironisnya, masyarakatlah yang membayar ongkos dari keputusan yang tidak pernah mereka buat. Sementara itu keuntungan komoditas ekspor sumber daya alam yang dihasilkan dari hasil kerusakan alam, hanya dinikmati sekelompok kecil pengusaha dan penguasa bahkan negara tetangga Singapura turut menikmati rente ekonomi karena devisa hasil ekspor mengendap di sana.
Ketika politisi abai, alam yang menagih. Alam tidak membuat perjanjian politik. Alam tidak menerima lobi. Ia hanya merespon kondisi fisik yang kita ciptakan.
Jika politisi membiarkan hutan diratakan demi rente, alam mengirimkan banjir. Jika politisi meremehkan sains, alam menjawab dengan longsor. Jika politisi memilih kenyamanan politik ketimbang tata kelola lingkungan, alam menunjukkan konsekuensinya—tanpa kompromi.
Oleh karena itu, harus dimulai dari politik, bukan hanya dari topografi.
Kita bisa menanam kembali hutan. Kita bisa memperlebar sungai. Kita bisa memperkuat lereng. Namun tidak ada restorasi lingkungan yang akan bertahan jika politik tetap tidak mampu melakukan audit lingkungan yang bebas dari intervensi politik, dan moratorium izin di wilayah ekologis sensitif.
Alam bisa dipulihkan. Tapi kemauan politik itulah yang lebih sulit direhabilitasi. Kita tidak bisa mengubah badai alam, tetapi kita bisa mengubah cara bernegara. Sudah saatnya Indonesia menetapkan tata kelola lingkungan sebagai pertahanan negara.
Peringatan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, “Jangan biarkan ada negara dalam negara!” telah terbukti dengan kenyataan timbulnya bencana banjir bandang di Sumatra, yaitu “ada negara keserakahan dan negara kebodohan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”
Tata Kelola Lingkungan
Bencana hidrometeorologis kini menyumbang lebih dari 90% kejadian bencana tahunan di Indonesia. Dengan intensitas hujan yang semakin ekstrem akibat perubahan iklim, Indonesia tidak lagi bisa memperlakukan isu lingkungan sebagai urusan formalitas atau sekadar syarat administratif.
Tata kelola lingkungan harus ditempatkan setara dengan pertahanan nasional, karena menentukan keselamatan jutaan warga, menjaga kestabilan fiskal negara—biaya bencana kini melonjak setiap tahun, dan melindungi daya saing ekonomi jangka panjang
Kejadian yang menimpa Sumatra merupakan jawaban dari sebuah keserakahan politisi, walaupun tidak semua politisi serakah, tetapi terlalu banyak yang memilih diam.
Kita perlu bersikap jujur, tidak semua pejabat atau politisi terlibat langsung dalam perusakan alam. Namun, dalam ekologi, diam adalah bentuk partisipasi.
Jakarta Selatan, 5 Desember 2025